Tuesday, December 28, 2004
...
Semua SMS, semua email, semua milis, menyampaikan kabar ini:
"mohon doa untuk saudara kami yang pergi mendahuilui di Aceh...YA, AKU SDH KTM MRK. ALHAMDULILLAH. MUJIZAT ALLAH SWT. SEPUPUKU, NENEKKU, KELUARGA BESARKU DI KP KEDAH HABIS SEMUA. MASYA ALLAH, BANDA ACEH JD KOTA BANGKAI MANUSIA...mohon doa juga untuk sepupu-sepupu kami..."
Ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan?
Sunday, December 19, 2004
ASTRAJINGGA
 Ini sisipan dari perang Alengka dengan Ayodya, ketika Dasamuka menculik Shinta dan Hanoman mengubrak-abrik kerajaan itu. Monyet putih itu, yang digambarkan sangat congkak dalam episode ini, hampir kewalahan ketika kakak beradik Aswandi Kumba-Kumba Aswandi tak kunjung bisa mati.
Ini sisipan dari perang Alengka dengan Ayodya, ketika Dasamuka menculik Shinta dan Hanoman mengubrak-abrik kerajaan itu. Monyet putih itu, yang digambarkan sangat congkak dalam episode ini, hampir kewalahan ketika kakak beradik Aswandi Kumba-Kumba Aswandi tak kunjung bisa mati.
Dua orang itu adalah anak-anak Kumbakarna, adik Dasamuka.Mereka tak membela Dasamuka yang memang salah itu, tapi upaya mencegah kerusakan yang lebih parah akibat amukan Hanoman. "Ini negara kami, kau tak bisa seenaknya merusak."
Tapi, tiap kali Hanoman membunuh salah satu dari mereka, selalu hidup kembali setelah dilangkahi oleh satu yang masih hidup. Hanoman pun mengadu ke Semar.
"Paman, bagaimana membunuh mereka? Saya sudah kehabisan tenaga."
"Ada cara tertentu," kata Semar.
"Makan singkong," celetuh Astrajingga, anak sulung semar, punakawan itu.
"Kok bisa," Hanoman terkejut dengan usul itu.
"Ya, bisa saja," kata Astrajingga dengan tenang.
"Bagaimana caranya?"
"Direbus."
"Direbus?"
"Direbus. Terus dimakan pasti kenyang dan punya tenaga lagi."
"Aeh, kutukupret!"
Aswandi Kumba-Kumba Aswandi pun mati dengan cara dibenturkan kepalanya. Mereka tak bisa hidup karena mati bersamaan. Alengka pun jatuh dan Shinta kembali ke pelukan Rama, meski harus menjalani pembakaran untuk membuktikan kesuciannya.
Monday, December 13, 2004
DONG, DEH
Saya punya teman yang suka menukar-nukarkan penggunaan kata "dong" dengan "deh", dan sebaliknya. Seperti kalimat "Kesiaaan deh lu" ia tuka rmenjadi "Cuciaaan dong lu" sambil menghibas-ngibaskan jari.
Ia punya alasan untuk itu. Katanya, "dong" dan "deh" sebenarnya dua kata yang sama. Jadi sah-sah saja dipakai untuk kalimat-kalimat yang sudah baku pemakaian dong dan deh itu. "Coba lu artikan 'kasian dong lu' dengan 'kasian deh lu', sama kan?" Saya tak langsung mengiyakan dalam omong-omong kosong suatu sore itu.
Ia menantang dicarikan lagi kalimat lain yang memakai dua kata itu. "Pasti sama," ia ngotot. Ia mencontohkan lagi. "Telepon gue dong sekarang, pasti akan sama dengan 'telepon gue deh sekarang'."
Di kamus (waktu omong-omong itu saya belum lihat kamus) dua kata itu punya pengertian berbeda. Deh adalah kata yang digunakan untuk mengukuhkan kata-kata atau maksud kawan bicara. Sementara dong adalah kata yang dipakai di belakang kata atau kalimat untuk pemanis atau pelembut maksud. Kelihatan bedanya? :(
Dan akhirnya (masih dalam omong-omong itu) ia menyimpulkan sendiri bahwa dong dipakai untuk permintaan yang memaksa, sementara deh untuk permintaan yang agak sopan. Saya langsung ngakak. "Kalau begitu, gue mau menodeh makan." Ia juga balas ngakak, "Pesenin gue sayur lodong ye."
Wednesday, December 08, 2004
VERONICA GUERIN
 Akhirnya bisa juga saya selesaikan menonton Veronica Guerin. Sebelumnya selalu terputus-putus: entah karena tertidur, atau sebab lain yang bikin kehilangan arah cerita sehingga jadi malas melanjutkannya. Rupanya, akhir film ini memang dramatis. Guerin, kita tahu, meninggal ditembak oleh gangster yang risih peredaran obat biusnya ditulis abis oleh Ronny.
Akhirnya bisa juga saya selesaikan menonton Veronica Guerin. Sebelumnya selalu terputus-putus: entah karena tertidur, atau sebab lain yang bikin kehilangan arah cerita sehingga jadi malas melanjutkannya. Rupanya, akhir film ini memang dramatis. Guerin, kita tahu, meninggal ditembak oleh gangster yang risih peredaran obat biusnya ditulis abis oleh Ronny.
Tapi bukan itu akhir ceritanya. Endingnya adalah ditangkapnya gembong mafia narkotika itu dan dihukum 28 tahun. Semua aset hasil penjualan obat biusnya disita oleh biro khusus yang dibentuk parlemen dan pemerintah Irlandia setelah kematian Ronny. Ribuan orang turun ke jalan setelah berita kematian Ronny tersebar di televisi: wartawan gigih itu menggelepar di jok mobilnya oleh enam peluru.
"Aku tak ingin menulis ini," kata Ronny, "tapi aku harus menuliskannya." Sebab 300 ribu anak-anak Irlandia jadi korban narkotika setiap tahun. Sebab setiap hari ada ibu yang menangis karena anaknya tewas di jalan tertusuk jarum suntik. Sebab pemerintah tak peduli.
Maka ia mulai menelusuri jejak peredaran itu dimulai dari anak-anak yang jadi pengedar. Ia punya teman, John Taynor, pengedar kecil yang punya rumah bordil dan jual beli mobil. Tapi, Ronny curiga. Tidak cuma itu saja si Taynor dapat duit. Ia punya BMW seri baru, juga peternakan yang luas. Ronny minta disambungkan kontak dengan "jenderal"-nya. Taynor menolak karena itu berarti nyawanya terancam.
"Dalam bisnis, diam adalah baik. Jangan sekalipun kau bertemu wartawan." Ini ucapan Johnny Gilighan, "sang jenderal" itu. Lewat penelusurannya, Ronny akhirnya tahu jalan mana yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke rumah Gilighan: sebuah kapel maha luas dengan 2 juta ekor kuda di dalamnya. Tapi, bukan pengakuan atau cerita tentang peredaran narkotika yang diterima Ronny, tapi sebuah pukulan yang meremukan tulang hidungnya.
Gilighan sudah gerah, Sunday Independent terus menerus menulis tentang narkotika pada halaman depannya setiap pekan. Sudah 12 bulan Ronny menulis itu setiap Minggu. Sebuah stamina yang luar biasa. Di sini, agaknya, jarang ada koran atau majalah yang tekun menulis sesuatu hingga ketemu biangnya.
Dan Ronny tewas di jok mobilnya, 26 Juni 1996. Justru ketika ia sedang merayakan kemenangannya karena dibebaskan pengadilan akibat ngebut di jalanan. Kematiannya menurunkan kejahatan di Irlandia hingga 15 persen. Orang-orang turun ke jalan menyeret bandar-bandar narkoba ke pengadilan.
Link :
Buku tentang dia diluncurkan setelah dua tahun kematiannya
Friday, November 12, 2004
MUDIK

Bisa jadi mudik, di sini, sudah jadi rukun Islam yang keenam :-)). Lebaran tak sempurna kalau tak mudik. Sensasinya bisa mengalahkan keruwetan jalanan. Kita bisa tahan menempuh kemacetan hanya karena ingin pulang. Dan saya begitu gembira mudik kali ini.
Tapi apa arti pulang sekarang? Kalau menyebut pulang orang bisa mengartikannya pada dua soal : pulang ke rumah kontrakan sehabis kerja; dan pulang dalam konteks mudik itu. Jakarta mungkin memang ditakdirkan jadi rantau yang asing. Kita malas balik lagi setelah melewati 1 Syawal.
Apapun lah. Ini kali hari sudah tak enak. Saya sudah mencium aroma rumah yang masih terpisah 15 jam. Selamat mudik. Selamat lebaran.
Tuesday, November 02, 2004
OH...YES, JENNA
 Jenna Jameson bikin buku! Barangkali tidak aneh jika orang Amerika menuliskan pengalaman seksnya. Ada Pamela Anderson yang sudah merilis Star: A Novel. Atau Paris Hilton yang menulis Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose. Tapi, keduanya terkenal sebagai selebritas yang menyebarkan atau disebarkan video-seks mereka. Tapi Jenna, dia bintang porno yang terkenal.
Jenna Jameson bikin buku! Barangkali tidak aneh jika orang Amerika menuliskan pengalaman seksnya. Ada Pamela Anderson yang sudah merilis Star: A Novel. Atau Paris Hilton yang menulis Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose. Tapi, keduanya terkenal sebagai selebritas yang menyebarkan atau disebarkan video-seks mereka. Tapi Jenna, dia bintang porno yang terkenal.
Dalam sepekan ini buku itu dinyatakan buku paling laris versi The New York Times.
Ia masuk bisnis itu sejak umur 17 tahun. Dan dua tahun bekerja profesional, berhubungan seks dengan puluhan laki-laki tanpa kondom. "Ajaib juga," katanya, "aku tak terkena penyakit seksual apapun." Jenna (30) kini punya anak perempuan dari hasil perkawinannya dengan Jay Gardina, pemilik studio film biru. Dan ia mengaku senang menggeluti pekerjaan itu seperti dikatakannya pada Anderson Cooper dalam sebuah wawancara di CNN Sabtu lalu. Dan Cooper, di televisi itu, terkejut-kejut saat mendengar jabawan Jenna yang tangkas dan polos untuk setiap pertanyaannya.
Para psikolog mungkin akan menebak pilihan Jenna seperti itu karena ia sudah yatim sejak kecil. Sementara bapaknya yang produser televisi mengabaikan hidupnya. Kini Jenna ingin anaknya kuliah dan jadi dokter. Dan berencana mengadapatasikannya menjadi film. Ada yang bisa meresensikannya?
Thursday, October 14, 2004
PUASA
Barangkali ini perasaaan sentimentil: saya sedih menjelang puasa. Barangkali juga perasaan entah apa. Rasanya ada yang hilang dalam menjelang besok subuh: saya tetap jauh dari orang-orang sekeliling. Tahun lalu juga mungkin sedih, tapi, ketika itu, saya memilih tak mengingatnya. Kali ini memilih itu bukan pilihan. Saya terpojok pada sentimentil itu.
Ada anak yang tak bisa dilihat penjam pelupuknya. Tak ada yang membangunkan dengan ruap aroma nasi setengah matang. Tak ada subuh yang ramai. Imsak itu tetap sunyi, hanya bunyi alarm yang terhenti sebagai pengingat. Lalu kembali sendiri.
Barangkali juga ada kenangan yang hilang tiap menjelang puasa. Kenangan pada bau pagi yang berkabut disusul ceramah lirih Kyai Balap. Ini kyai tak melulu berkotbah pakai hadits dan ayat lewat corong sebuah stasiun radio AM di kabupaten. Ia menunjukan dengan contoh sebuah perbuatan, dengan cerita yang jelas subyek dan predikatnya. Sebuah cerita yang kerap jenaka. Menghibur mengantarkan mata pada setengah merem dan setengah melek.
Kali ini semua itu tak bisa didapatkan lagi. Mungkin juga tak akan kembali lagi. Karena sekarang yang rutin memburu dan yang setumpuk kewajiban kerap datang menyergap.
Tuesday, September 21, 2004
ANAK KRISTUS
 Sudah tentu ini akan diprotes. Di Libanon, pusat Katolik di sana menyerukan mencabut peredaran novel ini. Tapi ditentang serikat penerbit: "Salman Rusdhi diburu, tapi Islam tetap ada. Dan jika Dan Brown juga diburu, Kristen tak akan punah." Itu kalimat Ahmed Fadlalla Assi. Dan Brown sudah menikmati 7,5 juta eksemplar novelnya di seluruh dunia.
Sudah tentu ini akan diprotes. Di Libanon, pusat Katolik di sana menyerukan mencabut peredaran novel ini. Tapi ditentang serikat penerbit: "Salman Rusdhi diburu, tapi Islam tetap ada. Dan jika Dan Brown juga diburu, Kristen tak akan punah." Itu kalimat Ahmed Fadlalla Assi. Dan Brown sudah menikmati 7,5 juta eksemplar novelnya di seluruh dunia.
Tapi memang mengejutkan. Melalui Da Vinci Code, Brown mengubrak-abrik kepercayaan Kristen dalam Perjanjian Baru. Menurut Brown, Yesus telah menikah dengan Maria Magdalena dan melahirkan anak perempuan bernama Sarah ketika Ia menahan sakit di bukit Golgota. Si anak ini kemudian juga beranak dan bercucu hingga melahirkan kelompok Priory of Sion. Sejak sepuluh abad lalu, kelompok ini bertahan dengan sembunyi karena menghindari amuk gereja.
Anggotanya para pangeran Inggris dan pesohor dunia: Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton, Victor Hugo...dan terakhir Jacques Sauniere, kurator di Museum Louvre, Paris. Kelompok ini terus menyiarkan keyakinan bahwa Maria Magdalena bukan pelacur seperti yang diwartakan Gereja. Kampanye negatif karena Maria diberi hak oleh Yesus untuk mendirikan Gereja. Maria adalah keturunan Keluarga Benjamin, seorang bangsawan. Brown lalu mengutip Kitab Matthew, Yesus adalah anak keturunan Raja Daud-Sulaiman. Jika dua orang ini bergabung akan membentuk sebuah kekuatan politis yang dahsyat dan berpotensi menggeser tahta raja-raja sesudah Sulaiman. Bukti lain lagi,Yesus orang Yahudi. Pada jaman itu, seorang yang tak menikah akan dikutuk.
Novel ini semakin menarik karena selapis-demi-selapis mulai menyingkap kode-kode rahasia yang disebar Sauinere yang dibunuh oleh rahib alibino, Silas--anggota kelompok Katolik koservatif: Ovus Dei. Robert Langdon, ahli simbol dari Harvard, dan Sophie Neveu, kriptolog di kepolisian Paris, adalah dua orang yang berkutat memecahkan kode itu sambil was-was karena dikejar oleh polisi pengadilan Paris. Polisi menuding Langdon adalah pembunuh Sauinerre, karena namanya ada dalam kode di samping mayat Sauinerre.
Perburuan kode itu dimulai dari menyingkap rahasia lukisan Da Vinci, Madonna of the Rocks, tempat menyembunyikan batu pengunci yang akan membimbing mereka ke Holy Grail, rahasia besar tentang keturunan Yesus yang berabad-abad disembunyikan. Selama petualangan dua hari-semalam itu, keduanya menemukan kaitan, teka-teki, anagram, dan kode-kode yang disebar Da Vinci dalam lukisan-lukisannya yang terkenal ke dalam sejarah Kristus. Dalam Mona Lisa, misalnya, tak hanya sifat androgini yang ditemukan melalui wajah misterius itu, tapi garis-garis dan cat blur itu menyimpan kode yang menghubungkan pada komunitas Sion yang pernah ada. Da Vinci adalah Grand Master kelompok itu.
Juga lukisan The Last Supper. Jika lukisan itu diperbesar maka orang ke-13 yang tampak bukan seorang murid Yesus yang sedang memegang cawan, tapi Maria Magdalena sendiri: sang Cawan Suci yang menadahi benih Yesus, Sang Real, chalice yang misterius itu. Da Vinci melukiskan dua orang itu tampak serasi: Yesus memakai jubah hijau, warna baju Maria. Santo Peter yang dibakar cemburu berbisik sambil menyodorkan bilah tangan ke Maria. Lalu penyaliban itu tiba, Maria harus lari untuk menyelematkan keturunannya.
Sejak itu keluarga keturunan Maria membentuk kelompok sembunyi-sembunyi. Dalam novel ini, Sophie adalah keturunan terakhir yang masih ada. Seluruh keluarganya terbunuh dalam kedok sebuah kecelakaan mobil. Ia kemudian bertemu dengan neneknya, yang sudah dinyatakan tewas dalam kecelakaan itu, di Kapel Rosslyn, Skotlandia, tempat terkuburnya dokumen Holy Grail. Brown mencurigai Disney, karena dalam kartun-kartunnya kerap menyuguhkan cerita tentang Holy Grail secara terselubung. Dan dari semua teka-teki itu pelaku utama yang berada di belakangnya adalah ...ah, baca aja sendiri.
Tuesday, August 17, 2004
RINGKAS
Betapa ringkasnya teks proklamasi itu. Hanya dua kalimat, dua paragraf, dan 27 kata. Betapa kalimat yang disusun Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarni dan Sayuti Malik itu langsung menukik ke inti: bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka, tak perlu alasan panjang, tak perlu retorika yang berbelit. Aneh juga, Soekarno yang suka berapi-api itu dan pandai menyusun kalimat dan menghidupkan bahasa dalam pidato-pidatonya, justru meminta Hatta membuat kalimat yang ringkas dan efektif. Mungkin karena ia sudah tak sabar memekikan kata Merdeka yang kerap ia teriakan saat memimpin rapat-rapat PNI semasa muda. Soekarno yang menulisnya dengan susunan kalimat yang didiktekan Hatta. Selembar teks yang menentukan sejarah Indonesia itu juga hanya diteken dua orang itu saja.
Tak seperti naskah proklamasi Amerika yang dirancang Thomas Jefferson lalu disusun bersama John Adams, Benyamin Franklin, Roger Sherman dan Robert L Livingstone pada 11 Juni 1776. Naskah yang panjang dengan susunan kalimat dan huruf abad 18 itu juga diteken oleh lima puluh enam anggota Kongres. Menarik juga, barangkali, jika diselisik kenapa penyusunan teks itu begitu berbeda.
Thursday, August 12, 2004
ECO, KUNDERA, DAN TERJEMAHAN
Lampung Post
Bagja Hidayat
SEORANG penerjemah, kata sebuah pemeo Italia, adalah seorang pengkhianat. Umberto Eco mengutip pepatah ini untuk menutup esainya di The Guardian Weekly. Esai berjudul A Rose by Any Other Name itu menyoal seni dan hasil terjemahan novel yang memasyhurkan namanya: Il nome della rosa (1980). Di sini, novel itu telah diterjemahkan dengan tak mengubah judul edisi bahasa Inggris: The Name of The Rose (2003) oleh dua penerbit Yogyakarta. Sebuah esai yang merisaukan seraya berkelakar—ciri khas Eco yang selalu berhati ringan—terhadap terjemahan sejumlah novelnya.
Dalam pemeo itu tak disebutkan penerjemah yang baik dan penerjemah yang buruk. Yang ada hanya pengkhianat. Baik Eco maupun pemeo itu juga tak menyebut penerjemah berkhianat pada penulis.
Eco, pakar semiotika di Universitas Bologna, Italia, adalah penulis yang kerap menyoal karya terjemahan, baik terjemahan novel dan tulisannya maupun terjemahan sastra secara umum. Ia bahkan merisaukannya. Setiap kali sebuah bukunya, atau secuplik tulisannya, akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ia selalu risau: bisakah gagasannya tersampaikan dengan bahasa lain? Karena setiap kata dalam suatu bahasa tak tergantikan oleh kata dalam bahasa yang lain. Kalau pun ada, kata dalam penerjemahan hanyalah padanan atau persamaan saja. Begitupun ketika The Rose difilmkan dengan judul sama oleh sutradara Jean-Jacques Annaud pada 1986, Eco mengatakan bahwa film itu bukan karyanya.
Setiap penulis, kata Eco, akan menemui dua situasi ketika karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Yang pertama tak acuh. Penulis macam begini punya dua kemungkinan yang lain: tak acuh karena tak mengerti bahasa terjemahan karyanya, atau terlalu bernafsu menerbitkan karyanya itu dalam sebanyak mungkin bahasa di dunia.
Sementara penulis yang lain juga tak acuh tapi dengan cemas yang tak lekas-lekas. Penulis kelompok ini justru merasa "terhina" ketika karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam bahasa Eco, penerjemahan merupakan "proses politik yang menyakitkan". Karena sebuah karya terjemahan berarti telah menumpulkan kejeniusan gagasan si penulis yang ternyata bisa ditiru dengan wadah yang lain, dengan bahasa yang lain.
Tidak setiap penulis, memang, menguasai pelbagai bahasa. Eco sendiri mengaku tak memahami bahasa Swedia, Hungaria atau Rusia. Ketika para penerjemah datang kepadanya dan menawarkan akan menerjemahkan novel Il nome della rosa ke dalam tiga bahasa itu, Eco mengizinkannya. Saat penerjemahan sedang berlangsung, Eco kerap kali bersepakat dengan penerjemahnya jika ada kata atau bentukan kata yang sulit dicari padanannya. Sebab itu ia menganalogikan penerjemahan dengan jual beli telur di pasar. "Jika pedagang minta harga 100 dan kau menawar 10 maka kalian akan bersepakat pada harga 50," katanya. Negosiasi seperti ini sering terjadi karena bahasa lain ternyata tak cukup menampung gagasan yang tertuang dalam bahasa asli. Meski negosiasi seperti ini tak meredakan kerisauannya, Eco kerap kali menerimanya setelah antara dia dan penerjemahnya alot berdiskusi.
Saat berdiskusi, ketika ada penerjemah yang tak mengerti gagasannya pada sebuah paragraf, kerisauan Eco makin bertambah-tambah. "Itu menunjukan pikiranku suram saat menulis paragraf itu," katanya. Jika sudah begitu, Eco kerap menjelaskan gagasannya dengan "bahasa" yang lain agar si penerjemah bisa mengerti. Ia akan menginterupsi dan mengajukan sebuah usul.
Dalam teori penerjemahan ada dua acuan yang dipakai para penerjemah yaitu berorientasi pada "bahasa sumber" atau orientasi pada "bahasa sasaran". Oleh Peter Newmark dua acuan itu dijabarkan menjadi delapan metode penerjemahan yang disebutnya Diagram-V, yaitu: (1) penerjemahan kata-demi-kata, (2) penerjemahan harfiah, (3) penerjemahan setia, (4) penerjemahan semantis, (5) saduran, (6) penerjemahan bebas, (7) penerjemahan idiomatis, dan (8) penerjemahan komunikatif. Menurut Newmark, hanya metode (4), (7), dan (8) yang hasilnya bisa disebut terjemahan.
Orientasi sasaran dipakai oleh William Weaver ketika menerjemahkan Pendolo di Foucault (1988), novel Eco yang lain, ke dalam bahasa Inggirs pada tahun yang sama menjadi Foucault Pendulum. Pada bagian 57, ketika Eco menggambarkan perjalanan tokoh utamanya di sebuah perbukitan, ia mengutip bait puisi Giacomo Leopardi, L'infinito, "al di la della siepe, come osservava Diotallevi". Pembaca Inggris, kata Eco, tak memahami bait itu karena tak hapal dan tak tahu Diotallevi. Sementara orang Italia, yang hapal luar kepala bait ini seperti orang Indonesia yang mengerti larik “Aku ini binatang jalang” dari penyair Chairil Anwar, akan langsung menangkap suasana perkampungan yang dikelilingi bukit-bukit bak pagar rumah lewat larik itu. Dengan pertimbangan rasa asing itu, Weaver kemudian menghilangkan kutipan itu. Setiap kali menemukan persoalan terjemahan seperti ini, kata Eco, "aku selalu tergoda untuk menulis ulang."
Milan Kundera, novelis kelahiran Brno, Republik Ceko, pada 1929 yang mukim di Prancis sejak 1975, dengan tegas menolak acuan yang dipakai Weaver ini Ia yakin dengan pandangannya bahwa sebuah karya sastra tak akan tergantikan oleh karya yang lain, sekalipun terjemahan. Baginya, "Sihir seni terletak pada keindahan bentuknya." Karena itu pengingkaran terhadap bahasa asli penulis akan mengurangi keaslian bentuk. Maka, misalnya, novelis yang terusir dari negerinya karena menulis sejumlah "novel politik" ini mengkritik hasil terjemahan The Castle karya penulis keturunan Yahudi yang tinggal di Ceko, Franz Kafka.
Dalam terjemahan The Castle (1926), Kundera banyak menemukan penyimpangan gagasan Kafka. Kundera, misalnya, mengkritik penggunaan persamaan kata dalam terjemahaan itu. Kafka yang menulis memakai kata-kata dasar dalam bahasa Jerman yang sederhana diubah menjadi kata-kata yang diberi imbuhan di sana-sini ketika diterjemahkan dalam Prancis atau Inggris. Kundera mengatakan upaya ini justru mengotori gagasan Kafka sendiri. Kundera menyebut para penerjemah seperti ini mengalami apa yang dinamakan "synonymising reflex". Penerjemah memperalat bahasa dengan mengulang dan mengganti kata dengan kata lain yang punya arti sama.
Khusus penerjemahan novel, dalam pengantar naskah drama Jacques and His Master (1994), Kundera mengatakan seperti ini: "Jika jiwa sebuah novel masih ada saat diterjemahkan atau ditulis ulang maka novel itu bernilai rendah." Kundera memang punya kerisauan lebih tinggi dibanding Eco terhadap karya-karya terjemahan atau karya adaptasi. Padahal pada awal karir kepenulisannya, Kundera juga seorang penerjemah.
Sikap keras itu tidak saja menjadi sikap dalam proses kreatif Kundera, tapi juga dalam kesehariannya. Sejak Juli 1985, Kundera menolak diwawancarai, melarang ucapannya dikutip, bahkan menolak menjelaskan novel-novelnya. Ia hanya mau wawancara secara tertulis dengan para wartawan atau editor. Ia menolak wawancara karena para wartawan sering salah kutip atau membuat pernyataan seolah-olah itu ucapannya, meski maksudnya bisa saja sama. Ia hanya akan menjelaskan novel yang telah diterbitkannya pada novel-novel terbarunya.
Karena itu dalam novel-novelnya Kundera membuat kamus mini untuk menunjukan maksud dari setiap kata atau istilah yang dibuatnya. Ia juga memberi penjelasan seputar latar, penentuan tema, atau pemilihan tokoh. Kundera, sebagai penulis dan narator, akan masuk terlibat dalam cerita untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang telah diciptakannya itu pada tokoh-tokoh barunya. Bentuk novelnya memadukan sejarah, biografi, musik, situasi politik, secara naratif atau bergaya esai. Seperti diakuinya dalam salah satu kumpulan esainya, The Art of Novel, bahwa sebuah novel harus mempunyai jiwa. Jiwa itu meneruskan jiwa novel terdahulu dan menjabarkannya lebih lanjut dalam novel terbaru.
Meski meragukan karya terjemahan, Kundera tak menolak karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Novel-novel Kundera sendiri dibaca dunia dalam bahasa terjemahan karena aslinya novel-novel itu ditulis dalam bahasa Ceko. Novel-novelnya dalam bahasa Ceko maupun Prancis telah diterjemahkan ke dalam lebih 22 bahasa. Sejak mukim di Paris, Kundera mulai menulis dalam Prancis seraya mengoreksi dan mengawasi kerja penerjemahnya, Eva Bloch. Novel L'Immortalite yang semula ditulis dalam Ceko lalu diselesaikan dalam Prancis ketika diterbitkan pada 1988 edisi pertamanya mengalami 14 kali cetak ulang dengan lebih 100 perbaikan pada setiap cetakan.
Ketika Yayasan Akubaca menerbitkan terjemahan novel ini menjadi Kekekalan (2000), hasilnya mendapat kritik pedas dari penulis Nirwan Dewanto. Dalam rubrik buku di majalah Tempo edisi 28 Januari 2001, Nirwan memberi judul resensinya itu dengan "Mencederai Kundera". "Kundera sesungguhnya pengarang yang tertib," tulis Nirwan, "kalimatnya yang jernih, lugas, dan tajam terasa hilang dalam terjemahan Indonesianya."
Seni terjemahan memang tidak mudah dirumuskan. Karena komunikasi yang terjalin dalam sebuah karya terjemahan tidak lagi teks dengan pembaca, tidak saja penulis dengan pembaca, tapi penulis, penerjemah, teks, dan pembaca sekaligus. Maka alangkah tepatnya pemeo orang Italia itu.
Wednesday, August 04, 2004
MATA BAYI
Tak ada yang lebih tenang selain mata bayi. Sudahkah kamu tahu wajahku ketika matamu kupandang lama-lama? Matamu melirak-lirik seperti tahu aku sedang omong atau aku sedang mendongeng. Matamu bersih dan tajam. Kalau menatap lekat-lekat, seperti sedang menelisik. Apakah setiap mata bayi seperti itu?
Tapi mata bayi belum berair. Setiap kali kamu menangis, air matamu tak keluar. Mungkin karena menangis hanya satu-satunya pilihan untuk mengatakan sesuatu. Waktu awal-awal kamu lahir, kamu jarang menangis. Hingga aku dan ibumu harus membangunkanmu jika kamu pipis atau be-ol. Kamu terus saja tidur tak peduli popokmu basah dan lengket. Tapi, kini, setelah tiga minggu, tangismu keras, menjerit-jerit, bikin ibumu kaget dan meloncat. Tapi, aku senang, bayi, kamu menjerit keras. Sebab menjerit bisa melatih kekuatan jantungmu, mengeraskan otot-otot di tubuhmu. Sejenis olahraga yang rutin.
Semalam tak kurang lima kali kamu menjerit. Aku hanya tahu kabarnya saja lewat sandek ibumu, tiap kamu bangun. Mungkin dia capai, mungkin juga bingung, mengangkat dan mengganti popokmu sendirian. Setelah kesakitan itu, bayi, ibumu masih harus menyiapkan dan mengatur tenaganya untuk itu. Semoga, kelak, kamu mengingatnya lewat catatan ini.
Tapi aku suka berpikir lain. Jeritan kerasmu mungkin karena matamu kini sudah awas. Sudah tahu sekeliling kamar, raut ibumu, juga warna-warna yang kau tangkap. Kamu mungkin masih asing. Bagaimanapun, dunia tak seenak rahim ibu. Sehingga, kata ibumu, jeritanmu makin keras jika popokmu tak segera diganti. Kubilang pada ibumu, memang, jangan cepat-cepat menggendongmu jika kamu menangis karena kamu bisa jadi manja. Kamu sudah tahu jika menjerit maka pelukan dan susu ibu akan menghangatkanmu.

Seminggu kemarin aku tak melihatmu. Hey, kakimu sudah menjuntai melebihi batas kasurmu. Dulu, panjangmu masih selebar kasur itu. Kamu juga makin berat. Ketika kugendong, punggung dan lehermu sudah kokoh. Dulu aku takut tiap kali menggendongmu. Tapi di rumah sakit itu aku tiba-tiba jadi mahir menggendong bayi, dengan was-was takut salah pegang, karena suster tak memberi pelajaran.
Aku jadi tahu kini. Jika kau percaya bahwa kita bergerak terhadap waktu, lihatlah bayi. Waktu amat berharga bagi mereka. Sebab, setiap hari mereka terlihat tumbuh. Setiap pagi adalah pertambahan usia bayi. Sementara aku, setiap bangun pagi, tak pernah memikirkan bahwa usiaku sudah berkurang satu hari. Aku terlalu nikmat dengan dunia. Tapi pada tubuhmu, waktu begitu kasat mata.
Seperti matamu itu yang kini makin tajam dan awas saja. Begitu hidup tak ada redup. Pelupukmu tenang jika sedang tidur yang lelap dan lama. Setenang danau yang ditumbuhi lumut dan batu juga pohon-pohon tua yang ada dalam fiksi-fiksi lama. Wajahmu damai. Sedamai itulah yang kutangkap dalam pemandangan desa yang dilukis para pelukis dengan pohon pisang dan rerimbunan pakis.
Monday, July 26, 2004
NAK...
Aku ingin bercerita bagaimana kamu keluar dari tubuh ibumu...
Sebuah sandek mampir ke ponselku. Dari ibumu. Kamu sudah mau keluar, katanya. Air ketubannya sudah pecah, juga darah. Aku hanya bisa membayangkan dari jauh sini ibumu tertatih ke rumah sakit. Kamar bersalin yang sudah kami pesan jauh hari tak jadi ditempati karena takut harus ada tindakan dokter. Tapi rumah sakit pun tak menolong. Semua dokter kandungan se-Bandar Lampung sedang seminar ke Bandung. Di telepon, ibumu meringis dalam cemas.
Kamu meronta sejak pukul 20. Itu 12 Juli malam--sepekan lebih cepat dari perkiraan dokter. Aku tahu itu, juga lewat sandek. Maka aku bersegera pulang dengan cemas yang tak lekas-lekas. Kamu akan keluar dini hari atau maksimal subuh menjelang fajar, kata perawat. Aku membayangkan, kamu akan menghirup udara bebas pertamamu ketika aku terjaga di selat Sunda. Itu berarti ibumu mengeluarkanmu dalam sendiri, sesuatu yang kami cemaskan sejak dulu.
Ada banyak godaan sepanjang malam itu. Orang yang duduk mengapitku di bus tak bersahabat. Mereka merangsek mempersempitku. Berkali-kali kuingatkan bahwa itu jatah kursiku. Tapi mereka hanya mendengus dalam tidur. Aku hampir saja meledak jika tak ingat sedang menunggu kelahiranmu. Kata orang, menunggu bayi harus juga mengekang marah. Agar kamu tak jadi pemarah. Baiklah. Marah memang tak baik sedang menunggu atau tak menunggu bayi.
Perjalanan tujuh jam itu begitu menyiksa. Malam jadi terasa lama tanpa mata terpejam barang sedetik. Lama yang makin mencemaskan.
Subuh itu tiba juga. Rumah sakit masih sepi. Pagi yang hening. Tak ada perawat atau petugas jaga. Aku harus berputar-putar mencari kamar bersalin yang tak dilengkapi papan informasi. Orang-orang yang kutanya tak ada yang tahu di mana kamar ibumu. Atau, mungkin karena aku juga sedang kalut. Butuh satu jam aku mengubek-ubek penjuru rumah sakit itu.
Akhirnya kama itu kutemukan juga. Tak ada jerit bayi. Aku makin cemas. Ibumu masih terbaring. Wajahnya kusut dan kuyu. Kamu belum keluar juga. Astaga. Dokter belum datang. Dokter umum yang akan menanganimu. Sementara kamu di sana terus meronta. Sudah bosankah dalam rahim ibu, Nak? Ibumu merintih tiap kali kamu meronta.
Dokter itu datang juga. Aku disuruh keluar. Aku tak ingat lagi bagaimana perasaanku menunggu di luar kamar. Yang kudengar hanya omongan dokter dan perawat itu, yang menyuruh menahan napas, hembuskan ,dan tahan lagi, kepada ibumu. Aku ingin menangis, Nak, mendengarnya. Kesakitan itu terasa juga menebas ulu hati. Setengah jam aku tak sadar dalam berdiri, ketika tangismu meledak, melengking memecah bening udara pagi. Aku sujud. Suara ibumu tak kedengaran.
Perawat keluar menggendong kamu. Aduh lucunya. Kamukah bayiku? Aku mengazani dan matamu berkedap-kedip. Kamukah bayiku? Bayiku yang kutunggu?
Kata dokter, tangan kirimu yang menghalangi jalan lahirmu. Tangan kiri mengepal di kepala. Wah, kamu sudah seperti pendemo. Atau kamu memang berdemo karena tak kunjung bisa keluar? Hingga jalan lahir itu harus dibelek dan kepalamu dijepit besi untuk menariknya. Ibumu hampir pingsan. Sakit kontraksi ternyata tak seberapa dahsyat dibanding ketika besi itu dimasukkan ke liang vaginanya. Ditembak pun aku tak akan merasakan sakitnya, katanya.
Sakit itu adalah sebuah alasan mengapa setiap anak harus mencintai ibu...
UPDATE: foto di usia 4 tahun.
Friday, July 16, 2004
KISAH PEMIJAT BUTA
Lampung Post, 16 Juli 2004
PEMIJAT buta selalu lewat di depan rumah saya, setiap pukul delapan kurang lima menit. Selalu saja tepat waktu. Kami sudah tahu dia datang sejak masuk jalan komplek perumahan. Tongkat besinya yang ia ketuk-ketukan untuk menuntun arah jalannya menjadi penanda pemijat buta telah tiba.
Baca Selengkapnya di sini: KISAH PEMIJAT BUTA
PEMIJAT buta selalu lewat di depan rumah saya, setiap pukul delapan kurang lima menit. Selalu saja tepat waktu. Kami sudah tahu dia datang sejak masuk jalan komplek perumahan. Tongkat besinya yang ia ketuk-ketukan untuk menuntun arah jalannya menjadi penanda pemijat buta telah tiba.
Baca Selengkapnya di sini: KISAH PEMIJAT BUTA
Tuesday, June 15, 2004
WASIT
Saya selalu kagum pada wasit, dalam setiap pertandingan sepak bola di Eropa, Amerika Latin, atau Asia--selain Indonesia. Di sana, wasit selalu berwibawa. Ia benar-benar menegakkan hukum sepak bola di lapangan hijau. Setiap detil pelanggaran ia pantau, seolah ia tak ingin kecolongan oleh kepura-puraan pemain. Yang melanggar disemprit, yang berbuat curang diperingatkan, yang melanggar dengan sengaja dikeluarkan.
Wajahnya pun tampil sangar, meski kadang juga melempar senyum jika memang ada yang harus dilempari senyum. Dia berlari ke mana bola menggelinding. Meski tak punya hak menyentuh bola, wasit adalah orang yang menentukan sebuah pertandingan. Dan kita menyaksikan sebuah seni di lapangan besar itu. Sebuah nasionalisme 90 menit, kata sosiolog Skotlandia, Grant Jarvie, meski tesis ini runtuh karena sepak bola ternyata menghilangkan batas negara ketika setiap klub boleh menyewa pemain asing.
Di televisi itu kita menyaksikan ketangguhan pemain Denmark dan wajah Vieri dan Totti yang frustrasi. Ada amarah dan cemooh. Tapi semuanya tak berakhir dengan rusuh. Jika emosi meletup, para pemain paling banter saling memaki, atau menyumpah wasit karena keputusan yang dianggap merugikan. Penonton pun riuh rendah di tempatnya. Bersedih jika tim dukungannya kalah, bersorak bagi yang menang. Wasit pun menunaikan tugasnya tanpa beban dan kekhawatiran akan digebuki jika satu tim kalah. Tak seperti kecemasan wasit-wasit yang memimpin pertandingan Persib-Persebaya.
Namanya juga pertandingan. Kata ini telah memiliki segalanya. Sepak bola, kata Antonio Gramsci, menuntut inisiatif, kompetisi dan konflik, tapi dia dikendalikan oleh peraturan tak tertulis tentang fair play. Barangkali bisa pula ditambahkan kini dengan kata "industri". Bisnis dan duit mengocor ke lapangan hijau beserta isinya.
Barangkali sepak bola juga kini sudah jadi indikator sebuah negara disebut maju. Hukum yang tegak di lapangan hijau itu adalah miniatur tegaknya hukum sebuah negara. Sepak bola bisa menjadi indikator ekonomi selain pertumbuhan, inflasi, dan nilai tukar. Negara yang bisa mengelola sepak bolanya dengan benar akan memenuhi kategori itu. Negara sepak bola adalah negara yang beradab.
Friday, June 11, 2004
JUMAT
I don't care if Monday's blue
Tuesday's great and Wensday too
Thursday, I don't care about you
It's Friday, I'm in Love
[The Cure | Friday, I'm in Love]
Selalu ada gairah tiap datang hari Jumat: kangen yang tertimbun, sebuah pertemuan, tapi juga bayangan sebuah perjalanan yang membosankan.
Saturday, June 05, 2004
MIMPI YANG MEMBOSANKAN
Ada mimpi yang menyenangkan, disebut mimpi indah. Ada mimpi yang menyeramkan, disebut mimpi buruk. Tapi tak ada mimpi yang membosankan. Dua-duanya bisa menyimpan tanda, dua-duanya bisa tak menunjukan apa-apa. Mimpi hanya realisasi dari keinginan-tak-sadar. Begitu Freud bersabda.
Itulah mungkin sebabnya kecengan kita di kelas sewaktu baru tumbuh jerawat dulu tak singgah di mimpi. Dia menjadi bagian keinginan-sadar. Dia menjadi bagian angan-angan, bagian yang diharapkan. Sebab itu yang datang justru Inneke K, seseorang yang hanya saya lihat di televisi, dulu, sewaktu tumbuh jerawat satu.
Dalam mimpi itu saya melihat diri sendiri melakukan sesuatu. Maksudnya, sesuatu duduk, sesuatu berjalan, sesuatu melamun, sesuatu berbicara entah apa. Saya tak pernah bisa mengingat dengan jelas gerak dan percakapan itu. Hilang ketika bangun. Lenyap ketika mata membelalak. Suatu kali, karena ingin mengingat, buru-buru saya catat suatu mimpi yang aneh tapi mengesankan sewaktu terbangun. Tapi saat mencatat itu pun pikiran saya kacau dan tak bisa menyusun kembali mimpi itu dengan persis. Setelah dibaca kembali, catatan itu bukan seperti sebuah mimpi.
Saya melakukan sesuatu di mimpi itu tanpa beban, sonder bosan, meski mimpi itu datang dari sebuah realitas yang menjemukan. Entah apa pula warna mimpi itu. Mungkin warna sepia seperti digambarkan orang-orang film.
Suatu kali saya nonton sebuah film indi yang lupa judul dan asal negaranya. Mungkin Timur Tengah, karena dari sana filmnya bagus-bagus. Pemain film itu hanya dua: kamera dan kadal gurun. Isinya melulu hanya gerakan kamera yang mengikuti gerakan kadal di hamparan pasir. Kemana kadal itu pergi ke sanalah kamera merekamnya dari jarak dekat. 40 menit hanya begitu saja. Capek. Bosan dan jengkel. Mual. Ia meneror. Film berakhir dengan menjauhnya kamera dari kadal yang masih berlari ke garis horison. Kamera seperti capek, secapek mata saya menontonnya.
Berselang kemudian, setelah bisa melupakan, film itu datang dalam mimpi. Saya lihat saya di sana menonton film itu. Menonton kejengkelan itu, melihat mual dan bosan itu. Tapi saya sebagai saya yang melihat saya di sana amat menikmati tontonan kemualan saya dalam mimpi itu. Saya si penglihat bahkan bisa mengendalikan saya yang ditonton harus bergerak seperti apa, meski ada beberapa gerak yang gagal dikendalikan. Tak ada bosan, tak ada jengkel. Tak ada mimpi yang membosankan.
Tuesday, June 01, 2004
PJKA
Seseorang selalu saya lihat berdiri di sana, dekat Damri yang sedang menunggu jam 22 di Stasiun Tanjung Karang. Memakai jas partai, selalu, warna hijau. Merokok dan necis. 40-an. Geraknya kaku karena takut jas itu kusut atau terlipat. Rambutnya licin pomade. Sepatunya juga mengkilap. Kalau memesan tiket, selalu dengan wibawa yang dibuat-buat yang ternyata tak sanggup menggentarkan nyali penjaga. Saya selalu melihat dia di sana, menunggu dengan dada yang mendongak.
Dia bagian dari orang-orang yang tergabung dalam PJKA atawa orang-orang yang "Pulang Jumat Kembali Ahad". Menengok istri dan anak-anak sehabis kerja seminggu di Jakarta. Menengok untuk menghabisi kangen yang tertahan, dan menjengkelkan. Lalu kembali lagi, ke Jakarta, juga dengan Damri. Lalu bertemu lagi dengan Senin pagi yang tak berubah: selalu macet.
Dia tak sendiri. Ada banyak penumpang Damri, setiap Minggu malam itu, yang saya lihat wajahnya itu-itu saja. Mereka pekerja, buruh, atau yang karena urusannya harus bolak-bolak Lampung-Jakarta. Ada yang sudah lima tahun merutin seperti itu. Ada yang tiga tahun. Ada juga yang baru mulai. Pantas wajahnya masih segar, tak ada gurat bosan.
Tidak setiap mereka yang kembali itu pulang lewat Gambir. Mungkin lebih banyak yang pulang putus-putus: ke Merak-naik kapal cepat ke Bakauhuni-naik taksi Kijang. Lalu kembali ke Jakarta baru pakai bus Damri, karena di Tanjung Karang tiket bisa dipesan dengan telepon, tidak seperti di Gambir. Atau tak ingin buru-buru kembali dengan naik kapal yang rusuh.
Pulang, bagi orang-orang PJKA, telah punya dua arti: pulang dari kantor ke rumah kos, dan pulang setiap akhir pekan, ke rumah, ke kampung, ke tengah keluarga. Ada banyak duit yang hijrah dan dibawa pulang orang-orang PJKA dari Jakarta.
Seorang teman juga tergabung dengan kelompok itu. Hanya dia ke Jogja. Naek Argo Bromo atau semacamnya, dan ketemu dengan orang-orang PJKA lainnya, dengan ongkos yang bisa cincai karena langganan. Tidur-duduk di lantai kereta, atau kalau yang beruntung, bisa menyelusup ke ruang resto. Yang ke Jawa Tengah atau Timur lebih punya ikatan kuat sampai membentuk klub PJKA segala. Setiap lebaran mereka saling mengunjungi.
Mereka orang-orang muda, yang baru setahun-dua beristri. Sedang menanti kelahiran atau baru punya bayi, seperti teman saya itu. Selalu ada saja lelucon di sana. Ketika naik kereta itu, mereka sudah berkaus. Kemeja dan dasi disumpal dalam tas. Duduk lesehan sambil melempar joke-joke baru. Kadang-kadang juga satir pada nasib yang mendamparkan mereka jadi anggota PJKA. Menyenangkan sekaligus mengharukan.
Monday, May 31, 2004
NGAMEN DOA
Kini sudah ada orang yang ngamen pake doa, di bus 86 jurusan Kota-Lebak Bulus. Masya Allah, di bus yang selalu penuh sesak selepas jam 4 sore, yang selalu menyimpan seabreg copet dengan kemampuan di atas rata-rata, ada orang di sana yang berdakwah. Mengutip ayat ini-itu, terutama tentang hidup sesudah mati. "Cintailah orang tuamu pasti kamu dicintai Allah," katanya, yang sudah saya dengar sewaktu mulai bisa melafalkan alif-ba-ta.
Aduh biung, gejala apa ini? Mungkin hanya orang malas kerja? Krisis yang belum berakhir? Kemiskinan? Ah, dia mengutip hadis lain tentang agama. "Agama itu adalah berbuat baik," begitu katanya. Seharusnya ditambahkan, agama juga berusaha dengan baik, dan dakwah dengan baik? Dipake ngamen, maksudnya. Mengumpulkan satu-dua receh.
Saya lihat dia cuma dapat seribu. Saya tahu ketika dari kantong bekas wadah permen itu ia mengeluarkan perolehannya karena kenek meminta tukaran receh seceng. Merunduk-runduk ketika menyodorkan plastik itu. Masih 40, cing! Mukanya masih bersih, dengan peci yang mencong. Mungkin belum terlalu lama terkena polusi Jakarta. Menyapu jalan juga bukankah pekerjaan halal?
Ah, Jakarta. Bikin orang betah mengutuknya.
Tuesday, May 18, 2004
DENDAM
Di Bandara itu, di layar tivi itu, Ferry Santoro melambai. Tersenyum. Matanya basah. Lalu merangkul istri dan anaknya. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Topinya hampir jatuh.
Saya menonton adegan itu dengan bulu tangan yang jadi kasap. 11 bulan bukan waktu yang sebentar dalam tawanan senapan, antara harapan pulang nama dan pulang badan.
Kita bersyukur ia akhirnya bebas. Ia mungkin akan segera menjadi konsumsi umum, lewat wawancara televisi, sehimpun paragraf di koran dan majalah, atau radio. Semua orang menunggu dan ingin mendengar bagaimana ia hidup dalam hutan-hutan Aceh. Mungkin ia juga akan segera bikin beberapa buku, biografi yang seperti novel, atau sehimpun cerita lewat rekaman gambar atau suara.
Tapi di televisi itu kita juga melihat di Aceh, para ibu dan anak-anak meraung, ketika suami dan ayah mereka diangkut ke Jakarta. Sebuah awal dimulai untuk hidup yang rudin, dengan cap yang tak kenal ampun: keluarga pemberontak. Anak-anak itu mungkin sudah "mati" ketika merengek pada susu ibunya. Sebuah gong dendam telah ditabuh untuk menebus penderitaan. Anak-anak itu akan mencatatnya dalam memori yang kelam, tentang sebuah perang...perang...perang!
Saya, mungkin juga kita, sulit merumuskan sebuah perasaan ketika melihat dan membayangkan situasi seperti itu. Pertikaian mungkin belum akan berakhir.
Thursday, May 13, 2004
GRAFOMANIA
Seseorang menulis sehimpun catatan harian pada sebuah buku tebal. Ia menulis dengan detil yang mengagumkan tentang apa saja yang ditemuinya dalam keseharian. Ia tak peduli untuk apa catatan riwayat hidup itu ia bikin. Seseorang itu hanya menulis, dan tak pernah dibaca lagi hingga kini, sampai menghasilkan bertumpuk-tumpuk diari.
Lalu, ia memasuki sebuah peradaban baru, sebuah kebebasan baru, sebuah peranti demokrasi baru, sebuah internet. Ia pun tak perlu buku tebal yang akan berdebu itu. Seseorang itu menuliskan sehimpun catatan hariannya di sana. Ia menulis seperti mendapat mainan baru. Ia terus menulis di sana ada atau tanpa pembaca.
Adakah ia, dan juga kita, telah menjelma jadi seorang grafomania? Istilah Milan Kundera untuk menyebut mereka yang menulis sehimpun catatan bukan untuk sebuah khalayak yang mereka kenal. Kaum grafomania, menulis apa saja yang ditunjukan untuk siapa saja, sayangnya mengenai hal-hal yang tak penting. Penulis blog yang sedang jatuh cinta akan menuliskan kekalutan perasaannya di halaman itu. Seorang grafomania, akan mencetak keasyikan itu dan menerbitkannya. "Versi lain dari kekuasaan yang mencemaskan," begitu kata Kundera.
Adakah ini masih berlaku? Internet adalah dunia yang diringkas: catatan putus cinta itu tercetak dan tersebar begitu kursor menekan papan "publish post".
Suara Kundera memang datang dari abad 20, ketika setiap negara punya batasnya yang tegas dan setiap warga negara punya identitas yang jelas. Ia sendiri disanjung di Eropa setelah terusir dari Ceko dan mendarat di Prancis. Tapi dengan itu Kundera seperti meneropong abad 21 yang ditandai dengan satu bagian internet yang merevolusi diari: weblog.
Wednesday, May 12, 2004
SETAHUN
: arline dan mikail
Tak selamanya lupa bisa membebaskan kita. Ini lupa tak menyeranta sewaktu ulang tahun tiba. Kita sudah setahun rupanya. Apa yang kita dapat? Jarak Bakauheuni-Merak yang jadi rutin dan terukur oleh jeda tidur sonder dengkur. Barangkali, sebab itu, setahun jadi jarak yang hampir lupa: tanpa i love u, candlelight dinner, atau sandek. Tapi percayalah, lupa ini tak akan menjerat cinta yang sudah terikat: padamu.
Wednesday, May 05, 2004
JULIAN PO
 Apa yang akan kaulakukan jika semua orang bertanya dengan menuduh: siapa yang akan kaubunuh? Padahal kau datang ke kota itu sekadar singgah, sebelum melihat pelangi yang megah, laut dan lembah, nun di sebalik wilayah. Maka, kau mungkin akan seperti Julian Po. Dia, dengan gugup dan berdegup, menjawab: membunuh diri sendiri! Orang-orang percaya, seperti bebas dari sebuah ancaman, lalu menanti apa yang akan terjadi pada akhir hidup seseorang.
Apa yang akan kaulakukan jika semua orang bertanya dengan menuduh: siapa yang akan kaubunuh? Padahal kau datang ke kota itu sekadar singgah, sebelum melihat pelangi yang megah, laut dan lembah, nun di sebalik wilayah. Maka, kau mungkin akan seperti Julian Po. Dia, dengan gugup dan berdegup, menjawab: membunuh diri sendiri! Orang-orang percaya, seperti bebas dari sebuah ancaman, lalu menanti apa yang akan terjadi pada akhir hidup seseorang.Begitulah. Julian Po kini sudah jadi misteri, sekaligus kekaguman, bagi orang-orang kota kecil Appalachia itu. Mereka datang silih berganti ke kamar losmen tempat Po menginap dengan bebas. Mereka ingin tahu sebab apa Po ingin bunuh diri. Bahkan seseorang menggelar lotre dengan satu taruhan, "Apakah Po akan mati hari ini?" Maka anak-anak, remaja, ibu dan bapak, menguntit kemana pun Po jalan-jalan menikmati cuaca kota itu.
Mungkin karena patah hati. Maka Lilah Wellech, yang masih bergairah di ranjang tapi punya suami impoten, menyambangi dengan busung dada dan mata menggoda. Lilah kecele, karena bukan karena perempuan Po berani mengakhiri hidupnya. Lalu ada Lely, si bisu pelayan losmen, yang juga menaruh hati pada sikap hidup pemuda Kroasia yang merekam hidupnya melalui kaset tape recorder itu.
Pendeta Bean tak kurang ibanya. Ia datang dengan Injil dan petuah tentang hidup yang berguna. Tuhan dan sorga. Po menjawab dengan enteng. "Hidup ini," katanya, "tak lebih dari penderitaan yang dipulas, buat apa juga susah-susah mikir Tuhan atau neraka." Bean kagum. Selepas itu ia campakan Injil dan mengumumkan kepada jemaatnya bahwa ia kini sudah tak ber-Tuhan. "Mungkin Dia tidak ada," katanya.
Lalu ada Sarah yang telah menunggu Po seumur hidupnya lewat petunjuk sebuah mimpi. Sarah telah merajut baju hangat yang khusus dibuat untuk menyambut kedatangan Po. Mereka pun terlibat asmara yang sulit dirumuskan. Selepas bersanggama, Sarah lari ke tepi jembatan. Di sana ia terjun. "Kita akan hidup selamanya di sorga,"tulis Sarah di secarik surat yang ia tinggalkan di ranjang. Sarah tahu, dan percaya, Po tak lama lagi akan menyusulnya lewat kematian.
Hidup Po makin kacau karena dirungrung keingintahuan orang-orang. Omongannya saat terpojok dulu itu kini telah jadi sebuah janji bagi warga. Dan mereka menunggu kapan hari yang tepat itu tiba. Lama janji itu tak kunjung dilaksanakan, bahkan dengan korban dan petaka, warga akhirnya datang menuntut. "Kapan kau akan mengakhiri hidupmu, Tuan Po?"
Po, tentu saja, tak bisa menjawabnya dengan cepat. Ia bilang besok. Padahal itu waktu yang sekadar diucapkan untuk menghindar pertanyaan. Pagi-pagi, Po mengepak kopernya. Ia berniat kabur. Tapi warga yang tak sabar segera menyeretnya kembali dan menanggih janji itu. Apa boleh buat. Po berjalan menunju pinggir kota ke tepi laut diiringi warga. Di sana, ia mengakhiri hidupnya. "Semua sungai bermuara ke laut," katanya," tapi laut tak pernah penuh." Ia pun menuntaskan keinginannya menikmati keanggunan pantai.
Ini film humor, sesungguhnya. Ceritanya menghibur tanpa harus ngakak. Ada yang mengendap dari kisahnya, saat di layar itu muncul Director by Alan Wade, lalu sederet nama pendukung film yang dibikin pada 1997 itu: apa jawabmu jika semua orang bertanya tentang sesuatu yang tak kau lakukan?
Monday, April 26, 2004
ANGKOT
Datanglah ke Bandar Lampung. Kau akan tahu ada klab jalan-jalan di siang hari. Sejak pertama mengunjungi kota ini lalu menetap dua tahun silam, angkot-angkot di sana selalu bikin saya takjub.
Jika kebetulan lewat sana, sesekali naiklah angkot dari Plaza Artomoro. Ke jurusan apa saja dan naik angkot warna apa saja. Ingat, tak tak ada nomor di kaca depannya. Kau yang buta warna, akan kesulitan membedakan warna ungu dan merah marun. Itu dua angkot dengan dua jurusan yang jauh berbeda.
Masuklah ke dalamnya. Kondektur akan memukul pintu dengan keras dan angkot akan berjalan lagi. Lalu nikmatilah perjalanan dalam klab jalan-jalan.
House music--ah, apa pula bahasa Indonesianya?, semacam musik pengantar triping--akan berdentam-dentam. Saya pernah mendengar sebuah lagu yang hanya ditemui di Stadium, Kota, semacam "Hey, DJ, tolong dong matiin lampunya sedikit! Tol...tol..tol...tol..tolong dong matiin lampunya sedikit! Kak-kak-kak-kak."
Hati-hati bagi yang lemah jantung. Kakimu mungkin bergetar akibat dentam itu. Suara itu datang dari spiker yang dipasang di ujung menghabiskan jatah dua penumpang. Angkot jadi terasa sempit. Ditambah pula dengan kain yang dipasang di atap dengan rumbai-rumbai yang menjuntai. Kain bendera sebuah klub sepak bola Inggris, atau Italia, atau bendera Amerika. Saya belum menemukan ada angkot ditempeli bendera Indonesia. Juga lampu yang berkerlap-kerlip hijau atau kuning atau merah.
Jika jok penumpang belel-belel, tidak begitu halnya dengan kursi sopir. Kursi itu dipasang serupa kursi mobil balap. Tinggi dan nyentrik dengan aneka warna cerah. Si Sopir memegang stir yang begitu mungil dengan perseneling yang tinggi sehingga mirip tongkat atau pemukul beduk. Di atas kepalanya, ya ini dia, tempat kaset musik ruangan itu diputar. Masuk akal juga, karena dari sana sopir dengan mudah mengecil atau membesarkan volume atau mengganti kaset.
Dash board tak utuh lagi. Kabel-kabel menyembul. Yang tinggal kini amplifier selebar bangku "ulang tahun" (kau mungkin juga pernah mendudukinya, itu, bangku yang di pasang dekat pintu, sehingga kaududuk menghadap penumpang lain). Di atas ampli itu ada jam, boneka, serangkaian huruf yang disambungkan benang, tempat kaset atau CD dan foto angkot itu dengan pintu depan yang dibuka dan si sopir bersedekap di sampingnya. Kaca depan tertutup dengan korden berenda. Dari foto itu kau akan tahu bagaimana rupa angkot yang sedang kau tumpangi. Ada tulisan besar-besar di kacanya semisal EROR, EMBER, dll.
Angkot bisa saja berhenti mendadak atau berjalan dengan gas yang tiba-tiba. Kenek itu akan berteriak, "Simpang, ya!" Jangan salah, itu kalimat tanya. Jika tak ada penumpang yang bilang "Simpang" juga, kenek itu akan memukul pintu lagi, "Kosong, ya!" Kau harus berteriak jika akan turun, karena dentam musik itu akan menelan suaramu. Jika tak cukup, pukullah kacanya atau tepuk pundak si kenek.
Sudah cukup nikmat? Jangan menggerutu, karena seorang penumpang akan dengan santai mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Asap mengepul. Lampu kerlap-kerlip. Angkot berjalan sedut-sedut. Musik jedur-jedur. Kurang apa lagi, kalau bukan sebutir-dua butir ekstasi. "Mabok, geh!"
Thursday, April 22, 2004
WARTAWAN
[Artikel yang menggoyahkan cita-cita jadi mantri kehutanan, heheh]
HARI ini saya menerima surat dari anak saya. Ia bercerita tentang pilihan masa depannya.
Goenawan Mohamad
* Catatan Pinggir Tempo tanggal 27 Oktober 1990 yang dibukukan dalam Catatan Pinggir 4.
Saturday, April 17, 2004
PARTAI
 Demokrasi memang tidak bisa menjawab banyak soal. Terutama ketika ia menyerah pada kekuatan jahat yang direstui banyak orang. Lalu kita ingat The Big Brother (oleh Landung Simatupang diterjemahkan menjadi Bung Besar) dalam novel George Orwell : 1984. Di sana yang jahat juga menjadi benar, karena diamini banyak orang, melalui partai--satu peranti dalam demokrasi. Novel gelap ini bercerita tentang hidup Winston Smith.
Demokrasi memang tidak bisa menjawab banyak soal. Terutama ketika ia menyerah pada kekuatan jahat yang direstui banyak orang. Lalu kita ingat The Big Brother (oleh Landung Simatupang diterjemahkan menjadi Bung Besar) dalam novel George Orwell : 1984. Di sana yang jahat juga menjadi benar, karena diamini banyak orang, melalui partai--satu peranti dalam demokrasi. Novel gelap ini bercerita tentang hidup Winston Smith.
Ia seorang laki-laki 39 tahun, seorang suami dari istri yang terlihat lebih tua, dan menderita kelainan pembuluh darah yang kerap menyiksanya. Winston tinggal di Victory Mansions, London, yang merupakan bagian Oceania--negara yang dipimpin si Bung. Orwell membayangkan dunia terbagi menjadi tiga belahan: Oceania yang meliputi Inggris dan Amerika, Australia, Atlantik; Eurasia yang meliputi Eropa, Rusia dan Afrika Selatan. Orwell menyebut nama Indonesia bersama Timur Tengah, India, Cina dan daratan Asia lainnya masuk ke negara Eastasia. Meski tak disebut jelas karena nama dan tempat terlalu fiksi, Orwell tengah menggambarkan dunia yang dicekam Perang Dunia II, ketika Stalin dan Lenin sedang menancapkan ideologinya.
Winston, karena hidupnya selalu terluka, merindukan hidup tenang yang ia pikir ada dalam Persaudaraan yang tak lain hanya perangkap partai si Bung. Maka Winston mendaftar ke sana melalui seseorang yang ditemuinya di jalan, O'Brien, yang kelak menyelundupkan sebuah buku pintar tentang politik, The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism. Buku itu, yang ditulis si Penjahat Masyarakat Emmanuel Goldstein mengajarkan bagaimana memutarbalikan soal-soal hidup. Dalam satu bab buku itu, misalnya, Goldstein merumuskan bahwa perang adalah kedamaian. Goldstein, seorang kanan yang merongrong pemerintahan partai si Bung dan punya acara televisi berjudul Dua Menit Benci, percaya bahwa kelanggengan dunia hanya bisa diwujudkan jika perang terus terjadi.
Winston percaya sepenuhnya pada pandangan hidup seperti itu karena didorong oleh keputus-asaannya menjalani hidup yang rudin (oleh Orwell orang-orang macam Winston di sebut kaum "proles", kaum bawah yang kurang lebih sama dengan "proletar" dalam rumus Karl Marx). Maka Winston terjebak dalam perangkap O'Brien yang kelak menyiksanya di kamar 101 Kementrian Cinta dan memaksakan pandangan-pandangan partai (membaca buku Goldstein adalah kejahatan yang tak terperi). Semacam cuci otak sebelum diterima jadi anggota. Winston, misalnya, dipaksa menerima 2+2=5 karena partai menghendaki demikian.
Winston tak menyangka jika langkahnya malah menjauhkan dari hidup tenang yang diimpikannya. Ia juga terpisah dari Julia, pekerja di Departemen Fiksi, si cuek-berambut hitam-26 tahun, selingkuhannya yang telah membangkitkan semangat hidupnya kembali. Ia dilarang melakukan hal-hal manusiawi oleh partai seperti menaruh minat pada guci antik karena itu bagian dari apresiasi seni. Bercinta dengan Julia semau keinginan mereka, bertelanjang di ranjang, atau mabuk jelewer di cafe Pak Charrington. Itu semua, menurut O'Brien si agen Polisi Pikiran, hanya akan menumpulkan semangat Persaudaraan saja. Winston takluk karena apapun yang dipikirkannya, apapun yang dilakukannya, akan diketahui oleh Polisi Pikiran dan wajah si Bung muncul memarahinya melalui layar-jauh-besar. Di Ocenia berlaku slogan yang kerap dinyanyikan setiap orang yang sekaligus jadi alarm hidup sehari-hari: "Big Brother is watching you", Big Brother is watching you, Big Brother...".
Winston baru tersadar bahwa pandangan Julia selama ini yang tak lagi mempercayai partai maupun acara Dua Menit Benci adalah benar belaka (meski pandangan Julia tak seradikal pandangan Tomas dalam novel Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being). Tapi ia sudah kecebur. Apa boleh buat. Otaknya sudah tercuci. Ia ingin lari dari Goldstein malah terperangkap di ketiak si Bung--yang bahkan O'Brien pun tak pernah melihat tampang aslinya.
Orwell seperti sedang meramal bagaimana ideologi kiri dan kanan, yang sama bahayanya, akan berhadapan muka pada tahun 1984 . Dunia menunggu apa yang akan terjadi pada tahun itu. Yang terjadi memang tak segenting apa yang diramal Orwell. Tapi ia telah dengan telak menanggambarkan abad 20 sebagai suatu masa yang rusuh oleh ide-ide yang melahirkan totalitarianisme di mana-mana. Kecemasan Winston dan Julia adalah kecemasan setiap orang pada demokrasi yang ternyata tak bisa menjawab semua soal, dan langgeng, ada di setiap zaman. Seperti kecemasan kita hari-hari ini sambil menunggu hasil perhitungan suara pemilu lalu.
Tuesday, April 13, 2004
RUMAH SAKIT
Saya jadi tahu, sekarang, begitu bisanya orang yang dulu bikin kata rumah sakit. Kata majemuk ini benar-benar menunjukan arti sekaligus fungsinya yaitu rumah orang sakit sekaligus rumah yang bikin sakit. Begitulah. Saya terbaring seminggu di kamarnya, dan hampir saja bertambah sakit seandainya tak cepat pulang.
Di kamar 5x5 meter itu, serba krem bukan putih seperti yang diilustrasikan para pencerita dalam kisah-kisahnya, saya tergolek bersama tiga orang pesakitan lainnya. Yang satu merintih sepanjang malam dan terbatuk karena jantungnya hampir copot ditambah paru-parunya yang hampir jebol. Dia bapak tua sekira 70 tahun. Renta dan keriput. Matanya hijau-tajam jika memandang orang pada tengah malam. Sepertinya ia belum rela jika Izrail datang tiba-tiba. Ia tertatih menuju toilet dengan selang infus yang menancap di pangkal lengan kanan jika malam telah larut. Dia terbatuk di sana, dengan darah dan ringis, lalu keributan anak-anaknya memanggil suster.
"Saya tak pernah merokok, tapi kenapa paru-paru ini jebol," katanya setengah mengutuk pada pagi sehabis sarapan. Orang-orang sakit itu bercengkrama tentang kesakitan-kesakitannya. Pada setiap pagi itu, ketika para suster yang tak ramah datang dengan lap dan obat, yang boleh tinggal dalam kamar hanya orang-orang sakit. Para penunggu diminta meninggalkan kamar. Obrolan kadang-kadang juga diselingi nasihat agar tabah. "Ini cobaan," kata si sakit yang lain, bapak setengah baya yang tergolek di samping saya.
Dia dibopong ke rumah sakit ketika pada suatu sore jantungnya akan berhenti berdetak. Dokter di rumah sakit itu tak sanggup menangani bilik kiri jantungnya yang tak bisa memompa darah. Bilik itu harus "dibalon" dan ia bingung mendapat biaya untuk pengobatan itu. Ia pulang dengan kebingungannya.
Seseorang yang lain, di seberang saya, anak muda 23 tahun. Renta dan gondrong. Paru-parunya tak terdeteksi oleh sinar X karena terhalang air yang menggenangi. Dadanya harus dibor dan ditancapkan selang untuk menyedot air-air itu. Ia suka begadang. Para penjenguknya anak-anak muda, teman-teman tongkrongannya yang datang dengan mulut mengepulkan asap rokok. Suster menghardik para penjenguk tak tahu tempat itu.
Sementara saya berbaring menahan demam yang datang malam-malam. Virus dengue ini telah menghajar ketahanan tubuh. Seumur-umur baru kali itulah tangan saya ditusuk jarum infus hingga dua kali karena selalu lepas plus setiap pagi jarum pengetes darah bolak-balik menusuk lengan kanan dan kiri.
Orang-orang itu merintih dalam diam pada malam yang jadi sunyi dan panjang. Menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang selalu terjaga, membayangkan yang mungkin dan tak mungkin, tentang kesakitan, umur dan kadang-kadang Tuhan. Maka saya memutuskan pulang sebelum dokter mengizinkan. Kamar itu sudah menambah beban kesakitan.
Thursday, March 18, 2004
MENUNGGU BAYI
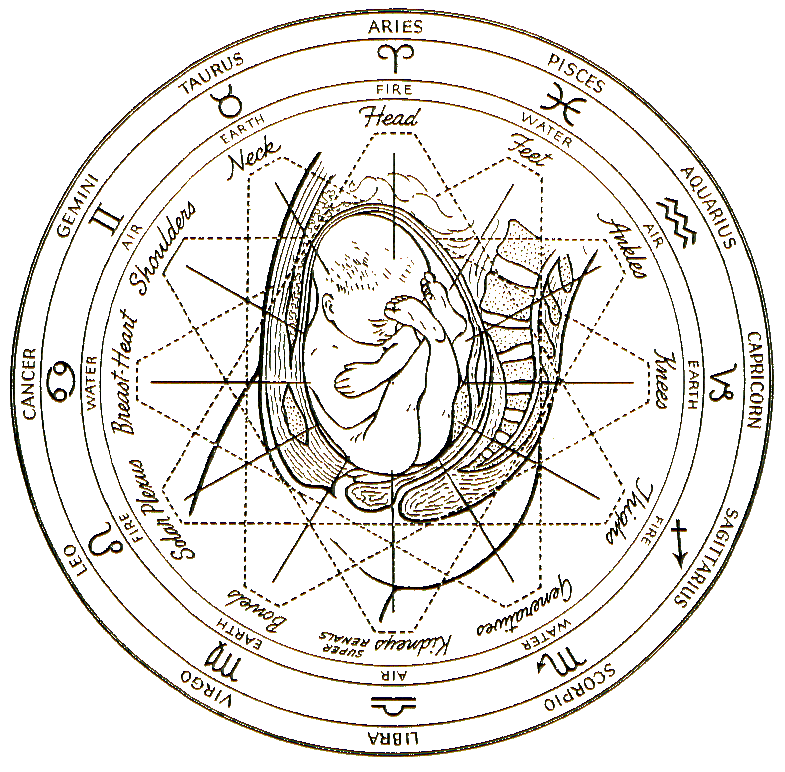 Aku menunggumu, Bayi, datang pada pelukan pada setiap sore yang anggun. Aku menunggumu, dengan debar yang tak bisa dirumuskan. Aku menunggumu, bukan karena aku telah meniupkan rabu di rahim ibumu. Aku menunggumu, karena aku mencemaskan sebuah petang yang tak tentram ketika ibumu berhenti menyulam.
Aku menunggumu, Bayi, datang pada pelukan pada setiap sore yang anggun. Aku menunggumu, dengan debar yang tak bisa dirumuskan. Aku menunggumu, bukan karena aku telah meniupkan rabu di rahim ibumu. Aku menunggumu, karena aku mencemaskan sebuah petang yang tak tentram ketika ibumu berhenti menyulam.Tak ada yang lebih mencemaskanku selain sore yang genting, tak ada renyai hujan, atau bau tanah basah, bayi menjerit. Mungkin hanya cemas yang umum dari debar yang memburu.
Aku suka membayangkan kamu di sana memandangku dengan mata yang masih terkatup, tersenyum, pipi yang merona lalu menguap dengan tenang, lewat pejam pelupuk ibumu. Apakah kamu tidur, Bayi, ketika aku amat ingin mengelus keningmu? Di pelupukmu itu, kelak, kecemasan-kecemasan ini, debar-debar ini, akan kukangeni sebagai sajak yang tak berjarak tentang sebuah episode yang menggagumkan.
Kusangka kamu perempuan karena ibumu kerap bermimpi tentang kupu-kupu yang menjelma tamu. Mengetuk pintu yang ditunggu. Maka kusiapkan sebuah nama, semoga kamu mau menerima. Tapi dokter menunjukan penismu lewat layar sonograf. Kamu meringkuk di sana. Ajaib bukan? Ada manusia di dalam manusia. Aku suka bertanya pada ibumu, bagaimana rasanya menghirup udara untuk dua nyawa? Seperti telah kutebak, ibumu menjawab dengan kalimat yang panjang, tak berujung, susah dicerna, tapi aku tahu maksudnya tanpa bisa merumuskannya kembali.
Maka kini aku sedang menyiapkan nama laki-laki. Agak susah, ternyata, menggabung-gabungkan huruf yang ada artinya atau tanpa artinya, yang enak didengar dan mengena. Ah, mungkin karena terlalu banyak kriteria. Padahal nama hanya satu tanda bahwa kamu orang yang berbeda, untuk kesepakatan sebuah definisi; seperti semua orang sepakat menamai bulan, agar orang bisa menceritakan keanggunanan cahayanya yang menimpa pecahan beling di pinggir kali. Shakespeare saja tak meminta nama itu pada bapaknya dulu.
Kadang-kadang, aku ingin menyerahkan saja padamu, nama yang kamu mau; yang bisa berubah setiap kali usiamu bertambah. Tapi kita lahir di dunia yang sudah bernama, karena itu dulu bapakku juga kesulitan mencari nama untukku seperti kakekku saat akan menamai bapakku. Kamu bisa saja menggugat karena aku tak memberi nama untukmu seperti teman-temanmu yang sudah bernama ketika kalian saling menyapa. Sebab itu aku kini sedang mencari nama, semoga kamu mau menerima.
Menunggumu membuatku membayangkan sebuah dunia yang tak lagi terjamah. Karena aku sendiri lupa kapan pertama kali bisa mengingat. Seandainya bisa aku ingin mendengar bagaimana rasanya berdiam dalam rahim ibu? Betapa sempitnya ternyata memori kita. Peristiwa-peristiwa seringkali lindap dan kita lupa mencatatnya. Ingatan yang menempel hanya betapa enaknya jadi anak-anak. Setelah itu dunia makin tidak enak karena ada kebutuhan dan pengetahuan. Aku khawatir tak bisa seperti Sosaku Kobayashi dalam pengalaman hidup Toto-chan.
Sebab itu, Bayi, menunggumu membuatku cemas, benarkah kamu datang sebagai sebuah pesan bahwa Tuhan belum bosan dengan manusia?
Friday, March 12, 2004
SESEORANG DI KURSI DEPAN
Seseorang di kursi depan sebuah bus yang melaju di Jalan Sudirman. Seseorang naik dari halte Ratu Plaza. Tak ada yang mencurigakan pada seseorang hingga bus tiba di halte Komdak. Penampilannya, saat naik, tak membetot mata untuk memandangnya lama-lama. Seseorang duduk begitu saja di kursi depan, dua baris diagonal di depanku. Hanya itu saja, tak lebih, sungguh, hanya itu saja.
Seseorang menarik perhatianku ketika bus masuk terowongan jembatan Semanggi. Rambut seseorang serasa kukenal. Pekat dan kriwil-kriwil tak kenal sisir. Seseorang memakai kemeja tentara dengan bordir beraneka gambar. Lambang Nazi segala di pangkal lengan kanan. Jins seseorang juga kumal. Mendekap ransel Alpina kumal dan robak-robek di jahit-jahitannya. Gaya seseorang mengingatkanku pada Jonggi, seseorang lain di masa lalu, aktivis partai yang teriak paling depan saat demo sebelum rusuh. Tapi Jonggi sudah "insyaf". Dia sudah pulang kampung. Dia hampir bersumpah tak akan singgah ke Jakarta lagi jika tak kucegah. "Siapa tahu kau jadi caleg," begitu kuingatkan.
Seseorang memang bukan Jonggi. Badan seseorang terlalu tegap untuk orang seperti Jonggi yang merokok tak henti-henti tanpa olahraga. Jonggi tak setinggi itu jika duduk. Lagipula untuk apa dia ke Jakarta musim kampanye begini. Dia sudah benci partai kini. Tapi siapa tahu dia berubah pikiran lagi dan bergabung dengan salah satu partai di kampungnya. Aku meyakinkan diri, Jonggi tak akan mau ke Jakarta. Seseorang bukan Jonggiku.
Sikap duduk seseorang mengingatkanku pada seseorang yang lain, juga dari masa lalu. Ada sikap Coki pada duduk tegap yang angkuh seperti itu. Membusung dada dan selalu menganggap remeh pada orang lain. Orang lain dianggapnya cupet meski aku tahu dia juga sering berpikir sempit terutama jika sedang jatuh cinta. Ia kerap tak bisa membedakan mana pujian mana cacian jika ada perempuan yang berhasil membuatnya kepayang, dan tentu saja, menolak cintanya.
Tapi ia bukan Coki yang bapaknya menurunkan gen rambut keriting lidi alias lurus atawa jocong. Coki di Jakarta dan kini sudah perlente jadi pekerja sebuah bank yang mulai pulih. Ia kini wangi dan mainannya ke kafe kalau tak nongkrong di mal mencuci mata untuk melihat belahan dada dan bokong abg. Coki jadi seorang metronis dengan gaji yang lebih dari cukup. Sudah tentu seseorang di kursi depan sebuah bus yang melaju di Sudirman bukan Cokiku.
Ingatanku melayang pada Gimbal, seseorang lain yang bernama asli Muhamad Zaki. Bentuk rambut seseorang mirip benar terlihat dari belakang ketika terakhir kami bertemu. Kudengar Gimbal pulang ke Aceh dan entah jadi apa. Kami tak ketemu kontak lagi. Ia juga tak tersambung internet, mungkin dia sendiri tak menyukai peranti itu. Gimbal ke Jakarta? Mungkin juga. Untuk apa? Ini yang perlu kutanyakan. Bus makin padat dan tersendat karena iring-iringan rombongan simpatisan partai. Ah, bagaimana membayangkan sebuah pertemuan dengan kangen yang mendadak?
Aih, tiga pengamen Batak naik pula berdesak-desakan. Seseorang satu menenteng gitar dan langsung menyanyikan Sajojo. Tiga suara berbeda, bergetar di setiap ujung nada, bertimpang tindih jadi harmonisasi yang enak didengar. Tiga lagu medley: semuanya berbahasa Batak. Sampai selesai mengumpulkan receh dari tiap penumpang. Mataku kini menubruk kepala seseorang di kursi depan lagi. Harus kulihat wajahnya agar penasaranku lenyap.
Dua orang penumpang berdiri hendak turun di halte Mid Plaza. Aku menggeser lutut. Seseorang di kursi depan berdiri juga, he. Aku juga ikut berdiri. Penumpang di belakang bilang permisi mau turun juga. Aku menggeser lagi. Pintu sudah terbuka, seseorang di kursi depan turun, aku mendesak tiga penumpang yang berjalan lelet. Sekilas kulihat wajah seseorang di kursi depan. Heh, dia Marko! Aku bersegera loncat dari bus yang terus melaju pelan. Marko, Marko, kapan kau tiba di Jakarta dan untuk apa?
Aku berdiri di trotoar di luar halte. Marko, seseorang berambut gimbal, telah lenyap.
: nama-nama disamarkan
Tuesday, March 09, 2004
BAHASA
SEORANG guru, Syaiful Pandu namanya, menuliskan keresahaannya di kolom surat pembaca majalah Tempo edisi terbaru. Dia bukan seorang epistoholic. Ia mungkin baru kali ini menulis surat pembaca dan mengirimkannya ke majalah terbitan Jakarta. Pak Syaiful hanya seorang guru yang cemas dengan pelajaran Bahasa Indoneisa. Pelajaran yang telah digelutinya selama dua puluh tahun lebih.
Ia cemas, karena itu ia menulis, "pelajaran ini dibenci sekaligus dipuji." Pak Guru Syaiful mengaku selama 20 tahun itu pula ia tak pernah objektif dalam memberi nilai pelajarannya pada siswa. Ia ingin memberi nilai 6 pada siswa yang tak becus membedakan "di" sebagai kata depan dan "di" sebagai awalan. Tapi rapat guru, dengan kompromi dan kekhawatiran pamor sekolah merosot, akhirnya memberi nilai minimum pada si murid itu sehingga bisa naik ke tingkat berikutnya.
Pak Syaiful protes. Ia kecam kebijakan pemerintah yang "semena-mena" menetapkan tiga pelajaran inti yang harus dikejar setiap siswa agar bisa lulus: Bahasa Indonesia, Inggris, dan Matematika. Pengkotakan ini, tulisnya, tak menjadikan siswa menguasai mata pelajaran yang disukainya. Mereka terpaksa belajar hanya agar nilai ujian tidak jeblog. Ia ingin kebijakan itu dicabut dan "jangan pilih kasih memberi nilai pelajaran."
Baginya tak jadi soal jika seorang siswa harus mendapat nilai 0 jika memang si murid tak mengusai sama sekali sebuah pelajaran. Siswa itu bisa lulus dengan sebuah nilai dari mata pelajaran yang ia sukai dan kuasai. Dengan begitu, katanya, setiap siswa akan terarah minat dan keahliannya. Pak Guru tahu bahwa sekolah bukan pabrik atau penjara (seperti yang dicemaskan di jauh hari oleh Tagore dan Ivan Illich). Sekolah adalah tempat pertemuan para siswa, tempat berbagi cerita, dan melakukan hal-hal yang mereka suka. "Kita hanya mengarahkan saja," tulisnya.
Pak Guru itu cemas regulasi tak mendukung sekolah sebagai tempat untuk memahami. Ia tinggal di Riau dan ia mencemaskan pelajaran Bahasa Indonesia. Agak mengkhawatirkan juga karena Riau adalah tempat bahasa Indonesia berasal. Dari sini banyak lahir para penulis yang punya minat dan jadi "perajin" yang tekun. Jika dari Riau saja seorang gurunya mencemaskan pelajaran ini, bagaimana dengan daerah lain yang baru mengenal bahasa Indonesia setelah Sumpah Pemuda?
Anak-anak Sunda atau Jawa yang setiap hari mendengar bahasa ibu mereka dan berpikir dengan bahasa daerah itu lalu diminta menuliskan pengalamannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak Sunda agak kebingungan jika mereka harus menuliskan "Saya memukul dia" karena dalam bahasa Sunda struktur kalimat itu jadi rancu. Di Sunda yang ada adalah "gebug sia ku aing". Mereka harus memutar "lidah" agar kalimat pasif di kepala mereka jadi kalimat aktif dalam tulisan bahasa Indonesia.
Pak Guru Syaiful pasti tahu bahasa Indonesia tidak cukup yang baik dan benar saja, tapi juga bahasa yang hidup: bahasa yang mampu menunjukan emosi dan nama-nama dengan tepat. Ia mungkin cemas tentang gejala ini ketika para siswa banyak terengaruh tayangan sinetron yang penulis skripnya tak bisa membedakan "di" itu, ketimbang pengajaran yang diberikannya. Karena itu ia perlu menulis kecemasannya di kolom surat pembaca.
Ia cemas, karena itu ia menulis, "pelajaran ini dibenci sekaligus dipuji." Pak Guru Syaiful mengaku selama 20 tahun itu pula ia tak pernah objektif dalam memberi nilai pelajarannya pada siswa. Ia ingin memberi nilai 6 pada siswa yang tak becus membedakan "di" sebagai kata depan dan "di" sebagai awalan. Tapi rapat guru, dengan kompromi dan kekhawatiran pamor sekolah merosot, akhirnya memberi nilai minimum pada si murid itu sehingga bisa naik ke tingkat berikutnya.
Pak Syaiful protes. Ia kecam kebijakan pemerintah yang "semena-mena" menetapkan tiga pelajaran inti yang harus dikejar setiap siswa agar bisa lulus: Bahasa Indonesia, Inggris, dan Matematika. Pengkotakan ini, tulisnya, tak menjadikan siswa menguasai mata pelajaran yang disukainya. Mereka terpaksa belajar hanya agar nilai ujian tidak jeblog. Ia ingin kebijakan itu dicabut dan "jangan pilih kasih memberi nilai pelajaran."
Baginya tak jadi soal jika seorang siswa harus mendapat nilai 0 jika memang si murid tak mengusai sama sekali sebuah pelajaran. Siswa itu bisa lulus dengan sebuah nilai dari mata pelajaran yang ia sukai dan kuasai. Dengan begitu, katanya, setiap siswa akan terarah minat dan keahliannya. Pak Guru tahu bahwa sekolah bukan pabrik atau penjara (seperti yang dicemaskan di jauh hari oleh Tagore dan Ivan Illich). Sekolah adalah tempat pertemuan para siswa, tempat berbagi cerita, dan melakukan hal-hal yang mereka suka. "Kita hanya mengarahkan saja," tulisnya.
Pak Guru itu cemas regulasi tak mendukung sekolah sebagai tempat untuk memahami. Ia tinggal di Riau dan ia mencemaskan pelajaran Bahasa Indonesia. Agak mengkhawatirkan juga karena Riau adalah tempat bahasa Indonesia berasal. Dari sini banyak lahir para penulis yang punya minat dan jadi "perajin" yang tekun. Jika dari Riau saja seorang gurunya mencemaskan pelajaran ini, bagaimana dengan daerah lain yang baru mengenal bahasa Indonesia setelah Sumpah Pemuda?
Anak-anak Sunda atau Jawa yang setiap hari mendengar bahasa ibu mereka dan berpikir dengan bahasa daerah itu lalu diminta menuliskan pengalamannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak Sunda agak kebingungan jika mereka harus menuliskan "Saya memukul dia" karena dalam bahasa Sunda struktur kalimat itu jadi rancu. Di Sunda yang ada adalah "gebug sia ku aing". Mereka harus memutar "lidah" agar kalimat pasif di kepala mereka jadi kalimat aktif dalam tulisan bahasa Indonesia.
Pak Guru Syaiful pasti tahu bahasa Indonesia tidak cukup yang baik dan benar saja, tapi juga bahasa yang hidup: bahasa yang mampu menunjukan emosi dan nama-nama dengan tepat. Ia mungkin cemas tentang gejala ini ketika para siswa banyak terengaruh tayangan sinetron yang penulis skripnya tak bisa membedakan "di" itu, ketimbang pengajaran yang diberikannya. Karena itu ia perlu menulis kecemasannya di kolom surat pembaca.
Wednesday, March 03, 2004
YANG LEBIH INDAH
Grey is my favorite color
I felt so symbolic yesterday
[Mr Jones | Counting Crows]
Manakah yang lebih indah, puisi atau teks lagu, sebuah prosa atau tayangan kriminal di televisi? Barangkali kita sulit membedakan mana yang lebih mengagumkan di tengah zaman ketika cerita yang seharusnya hanya ada dalam prosa meruyak dalam kehidupan nyata, mengisi halaman-halaman berita. Kita sulit menentukan mana yang lebih bagus ketika sebuah lagu kini dihargai pada seberapa bagus seseorang menciptakan liriknya, tidak sekedar nada yang mengalun-alun.
Nikolai Chernyshevskii mungkin akan bersorak jika ia masih melihat bulan beringsut sekarang. Ia akan menunjuk, "Lihatlah," seraya bergegas meninggalkan taman yang rimbun, "bulan tak lebih bagus dari lampu pijar di Sudirman." Barangkali, ya, barangkali saja seperti barang di kali yang mengambang, Chernyshevskii memang menulis Hubungan Seni dan Realitet untuk ini zaman yang sudah ndableg. Ia tak cocok ketika hidup di suatu masa di mana semboyan seni untuk seni menghadangnya.
Betapa kini realitas telah merampas apa yang dulu diimajinasikan orang. Dalam dunia yang telah diringkas sedimikian pendek dan tak ada sekat ini realitas jauh lebih mencengangkan dibanding sebuah cerita pendek di halaman koran pada hari Minggu. Kita tak mendapat kejutan pada pagi seraya menyesap kopi di beranda itu. Cerita-cerita berhamburan tak membekas dan nama-nama berseliweran tanpa berhenti menjadi "tokoh".
Kita lebih terkejut pada sehimpun berita yang menayangkan perampok tak berkaki melumpuhkan satpam dan anjing galak di televisi. Kita lebih terkejut ketika seseorang yang ketahuan berbohong diakui sebagai pahlawan. Dengan teknologi orang akan bisa menciptakan senja yang muram yang dulu kita jumpai dalam cerita-cerita Seno Gumira Adjidarma lalu menghadiahkannya kepada pacar sebagai kado Valentine.
120 tahun kemudian mungkin apa yang dibayangkan Tolkien dalam dunia Lord of The Rings akan menjadi kenyataan. Sekolah-sekolah semacam Hogwarts akan dibuka dan anak-anak berduyun mendaftar untuk mendapat sapu terbang. Apa yang disebut Polisi Pikiran yang dibayangkan Orwell dalam 1984 pun akan menjelma menjadi sebuah divisi sendiri di Mabes Polri. Dunia sudah menjadi prosa.
Monday, March 01, 2004
BIARKANLAH MEREMBES
: Untuk Avid yang risau
Bagi yang khawatir, pernahkah dia mengkhawatirkan kekhawatirannya? Setiap suku lahir, membentuk komunitas, tapi pernahkah mereka, pada mulanya, memproklamirkan kesukuannya. Setiap suku lahir dan nama-nama diberikan kemudian. Kata orang Jawa, kata Sunda berasal dari dua kata: asu dan anda. Dan kita ingat cerita tentang Tumang dalam hikayat Tangkuban Parahu. Setiap anak Sunda pasti tahu cerita yang terkenal ini.
Tumang menjadi tokoh yang tersisih dibanding Dayang Sumbi atau Sang Kuriang. Riwayatnya terhenti ketika Sang Kuriang, anaknya sendiri, membunuhnya saat berburu dan mencongkel hatinya untuk diberikan kepada Dayang Sumbi. Tumang tersisih, bukan karena dia sebagai anjing, tapi karena folklor itu juga, agaknya, tak menginginkan cerita besar yang ingin ditampilkannya mengusung Tumang sebagai salah satu tokohnya. Pengakuan pada Tumang hanya sebatas dia sebagai penyebab Sang Kuriang lahir.
Tumang hadir dalam cerita ini ketika ia mengambilkan "taropong", bambu penggulung benang tenun, milik Dayang Sumbi yang jatuh ke kolong gubuknya yang bertiang tinggi. Dayang Sumbi "terpaksa" menjadikan Tumang sebagai suami karena janji yang telah dibuatnya sendiri: "Bagi laki-laki yang bersedia mengambil kainku akan kujadikan suami, dan bagi perempuan akan kujadikan saudara." Putri raja ini agaknya tak memperhitungkan di hutan yang sunyi akan ada manusia lain yang mendengar janjinya itu. Maka Tumang, anjing jantan itu, datang dan lahirlah Sang Kuriang.
Akibat kebohongan Sang Kuriang yang memberikan hati anjing itu pula, bukan hati kijang, Dayang Sumbi kemudian mengusir anaknya dengan satu tanda ayunan sinduk ke kepala Sang Kuriang. Luka di kepala itu kelak yang membuat Dayang Sumbi tak sangsi, pemuda yang melamarnya tak lain anaknya sendiri. Garis cerita kemudian berkutat antara cinta Sang Kuriang yang ditolak kepada ibunya, pembuatan perahu yang tak rampung, dan seterusnya. Setiap anak Sunda mengira kilat yang mengguntur di langit saat hujan adalah penanda Sang Kuriang hampir berhasil menangkap Dayang Sumbi.
Dalam libretto Sang Kuriang (1959), Utuy Tatang Sontani meyakini anjing di sana bukan binatang, melainkan manusia tanpa daksa, yang tuli, yang bisu, tapi setia. Manusia golongan rendah yang pasrah, tak bisa mengelak, saat tombak anaknya sendiri menghantam tubuhnya yang ringkih. Hingga kini belum ada yang menganalisis kenapa hikayat itu menciptakan anjing sebagai asal mula sebuah cerita, bukan hewan lain yang lebih terhormat, misalnya. Karena dalam Islam anjing digolongkan ke dalam hewan najis. Juga babi, yang menjadi ibu Dayang Sumbi. Ajip Rosidi dalam Manusia Sunda (1980) menolak anekdot Jawa yang tak ilmiah itu. Karena hikayat bukan sejarah, katanya. Tapi ia tak membahas lebih detil kenapa anjing yang mempersonfikiasikan Tumang.
Terlepas dari itu, dongeng-dongeng yang hidup di kalangan orang Sunda selalu melukiskan gunung dan sawah, baik sastra klasik, sebelum atau sesudah kemerdakaan, bahkan hingga kini. Dalam sebuah sajaknya, Acep Zamzam Noor menghubungkan seorang petani yang mengayun cangkul, berkutat dengan lumpur di sawah, dalam kesunyian dan kesendirian, dengan gerakan orang yang sedang sembahyang. Dalam Priangan si Jelita, Ramadhan KH menulis sajak panjang yang mempesona tentang lembah-lembah, sawah, pematang, gunung yang cantik.
Jarang sekali para penayir itu melukiskan Sunda sebagai sebuah metro. Sifat-sifat tokoh dalam sastra Sunda pun tak ada yang keluar dari watak dalam folklor yang dimiliki Si Kabayan, Mundinglaya di Kusumah, Purbasari Ayu Wangi, atau Sang Kuriang yang teguh pendirian. Sosok Kabayan muncul dalam Cepot yang doyan banyol dalam wayang golek atau Karnadi dalam cerita Rusiah Nu Goreng Patut (1927) karangan Joehana. Sifat Mundinglaya sebagai ksatria muncul dalam diri Raden Yogaswara sebagai Mantri Jero karya R Memed Sastrahadiprawira. Atau sifat kedewian Purbasari muncul dalam Dewi Pramanik dalam wawacan Purnama Alam karya R Suriadiredja. Agaknya folklor di manapun, selalu muncul seiring dengan keinginan komunitas itu untuk menampilkan identitasnya dalam bentuk sastra lisan. Kota, agaknya, dianggap tak membumi.
Orang Sunda juga tak pernah ekslusif. Setiap cerita dalam sastra atau folklor selalu menampilkan tokoh utama yang keluar dari tanah kelahiran--meski agak mengherankan kenapa orang Sunda tak terkenal sebagai bangsa perantau. Padahal, dalam satu cerita tertua yang mengisahkan penemuan agama Islam mula-mula di Cirebon, tokoh utama sejarah itu melanglang hingga ke Jawa. Islam kemudian memang agama yang paling diterima oleh orang Sunda yang masih menganut Hindu atau Wiwitan. Barangkali, karena orang Sunda--juga seperti orang Jawa--menganut falsafah "mangan ora mangan asal kumpul".
Sejarah Sunda juga mengisahkan keterbukaan menerima budaya dari bukan Sunda. Ketika pasukan Mataram mendarat di pesisir Banten, misalnya, kemudian melahirkan barter barang antara tentara Mataram dengan orang Kanekes di sana. Mataram yang pesisir menukarkan ikan dan hasil laut lainnya dengan kebutuhan dari hasil pertanian. Orang Sunda, mula-mula, hidup di gunung-gunung. Mereka terdesak oleh budaya Utara yang lebih radikal. Mereka selalu menghargai tamu--bahkan menghormatinya sebagai pembawa budaya yang lebih maju (paling tidak tamu adalah orang yang berpesiar)--sesuai dengan falsafah "datang katempo tarang, indit katempo birit". Tamu yang menghormati sopan santun akan lebih dihormati lagi, bahkan secara tak sadar, jika ia menyebarkan misi budayanya. Para penulis sastra kuno di Sunda pun, begitu catatan Ajip, bukan lahir dari orang Sunda murni. Mereka datang ke Sunda karena salah satu orang tuanya kawin dengan orang Sunda lalu menentap di sana. Mien Resmana yang carita-carita pondok-nya selalu menarik punya Bapak orang Bugis.
Karena itu Avid, menampilkan Sunda dengan lebih terhormat, menurut saya, bukan dengan memunculkan ekslusifitas, gaya, dan bungkusnya. Budaya Sunda, sejak lahir, sudah mendekam dan muncul dalam komunitas Sunda sendiri. Sebab itu juga, menurut saya, kesundaan juga tak akan punah. Jika sekarang Bandung, sebagai pusat Sunda (benarkah penyebutan ini?) sudah didominasi oleh sifat-sifat metro, itu hanya karena ke Bandung telah menyerap apa yang disebut lanskap kota. Kota, kata Raymond Williams, (adalah lanskap besar yang) selalu menampilkan kesunyian dan keterpencilan dari identitas asalnya. Cobalah kita tengok ke selain Bandung, apa yang disebut Kesundaan di sana masih muncul. Dulu, di depan Balai Kota Bogor setiap malam minggu selalu ditampilkan wayang golek atau calung. Orang Bogor berduyun menonton pentas itu.
Saya khawatir Kesundaan yang dibungkus dengan ekslusifitas, yang mentereng, hanya akan memberhentikan Kesundaan sebatas panggung--lengkap dengan birokratisasi segala. Maka biarkanlah Kesundaan itu muncul dan merembes di setiap jiwa orang-orang Sunda baik yang di komunitas yang getol, mapun di luarnya. Saya kira, Mangle yang berkertas Cosmopolitan itu agak aneh juga jika cerita pendek di sana menceritakan bagaimana orang seperti Karnadi ngadu untung ka kota. Lakon Perjuangan Suku Naga WS Rendra agaknya pas melukiskan itu. Di sana apa yang "kota" pada akhirnya memenangkan pergulatan. Tapi ini zaman ketika kapitalisme sudah diamini banyak orang baik sadar atau tak sadar, dan gaungnya sampai ke pelosok dibawa oleh "Karnadi-Karnadi" yang pulang kampung. Jika anak-anak Sunda sekarang jarang berbahasa Sunda, itu karena sedikitnya orang Sunda yang mau menulis dengan getol dan melahirkan tulisan-tulisan yang punya ruh Sunda yang kuat. Sebagai "pemerhati" tentu saja dikau harus tertantang.
Ada banyak hal yang belum terungkap dalam sejarah Sunda yang panjang. Ada bahan perdebatan menarik, sebenarnya, ketika Ayatrohaedi meragukan nenek moyang orang Sunda. Menurut tulisannya di Pikiran Rakyat, nenek moyang orang Sunda bukan Ciung Wanara. Seharusnya ini didebatkan, karena dalam pantun lisan, kita tahu, Ciung Wanara adalah orang yang diklaim nenek moyang orang Sunda, yang bertempur melawan Hariang Banga di tepi sungai Cipamali. Menurut Ayat, pengakuan itu barangkali dipicu oleh asal turunan. Ciung Wanara adalah anak dari istri yang sah Ranghyang Sanjaya, bukan anak selir seperti Banga. Ini baru praduga yang seharusnya ditelusuri untuk menemukan mana yang benar. Juga sejarah Ciung Wanara sendiri yang namanya tenar hingga ke Bali--di sana I Gusti Ngurah Rai memimpin laskar yang diberi nama Ciung Wanara. Ini dunia yang tak habis-habis untuk diteliti dan diperbincangkan. Karena itu, Vid, pernahkah khawatir dengan kekhawatiranmu?
UPDATE:
Avid menuliskan tanggapannya di sini
Friday, February 27, 2004
Thursday, February 12, 2004
THE NAME OF THE ROSE
NOVEL ini bercerita tentang sebuah pertanyaan yang menggema di sebuah biara di pinggran Italia pada sebuah musim salju akhir November 1327. Biara yang menjadi tempat utama berlangsungnya cerita dalam novel Umberto Eco, profesor semiotika di Universitas Bologna, Italia : The Name of The Rose. Aslinya, novel ini terbit dalam bahasa Italia dengan judul Il nome della rosa pada 1983. Pernahkah Kristus tertawa?
Para rahib muda, yang setiap hari bergulat dengan ribuan kitab di perpustakaan di antara kegiatan rutin biara, memunculkan pertanyaan itu dalam diskusi sembunyi-sembunyi. Adalah Jorge yang menentangnya. Bagi rahib tua yang buta ini, Kristus tak pernah tertawa. "Kebenaran dan kebajikan bukan untuk ditertawakan. Inilah mengapa Kristus tak pernah tertawa, tertawa menyebabkan keragu-raguan," katanya (hal. 203).
Untuk mengusut perilaku bidah dalam biara itu diutus William dari Baskerville, seorang bruder Franciskan asal Inggris. William datang ditemani seorang calon rahib dari Jerman, Adso, si "aku" dalam novel tebal ini. William, seorang intelek yang telah merambah pelbagai ranah ilmu pengetahuan, hidup di zaman ketika gereja dan kepausan sedang kehilangan pamor. Ordo Franciskan berperan sebagai penentang utama Paus Yohannes XXII (1316-1334) yang menyerukan agar gereja yang bergelimang kemewahan kembali hidup miskin seperti ajaran Kristus. Sementara di seberang yang lain berdiri para raja dan kaisar yang menginginkan kerajaan lepas dari kekuasan Paus. Perselisihan tiga kubu itu memuncak ketika diberlakukan hukum bakar bagi para pengikut Santo Fransiskus dan siapapun mereka yang mengecam gemerlap hidup Paus.
Tapi di antara saling-silang sengketa itu, toh ada juga upaya untuk menyatukan perbedaan pendapat. Dalam novel ini, pada hari ketiga, Eco mengisahkan, kubu-kubu itu saling bertemu dan berdebat di biara megah itu meski tak mencapai kata sepakat. William, selain bertugas mengusut bidah, adalah salah satu utusan dari kubu penentang Paus. Namun, belum juga pertemuan itu digelar, William dan Adso sudah dikejutkan oleh kematian seorang rahib yang jatuh ke dasar jurang pada hari pertama kedatangan. Kematian Adelmo, si rahib itu, tak berdiri sendiri. Kematiannya diikuti oleh serentetan kematian rahib-rahib lainnya. William tergerak untuk menyelidiki kematian yang misterius itu.
Eco, agaknya, telah dengan cermat mempersiapkan tokoh William. Karena asal William mengingatkan kita pada sebuah cerita detektif Sherlock Holmes yang terkenal: Anjing Setan dari Baskerville. Begitulah. William dan Adso menjelma dua orang detektif yang tangkas. Keduanya bahu-membahu menguak misteri tujuh kematian selama tujuh hari, seluruh waktu dalam novel ini. Dalam investigasinya itu, William masuk ke dalam lorong-lorong perpustakaan biara yang dihuni ribuan naskah dan kitab pada malam hari, waktu di mana peristiwa penting selalu terjadi. Ia mengumpulkan bukti, menanyai saksi, menguraikan simbol-simbol rahasia dan kode manuskrip serta menghubung-hubungkan pelbagai peristiwa di seputar kematian itu. Ia mengurai sengkarut misteri itu dengan analisis logika a la Francis Bacon, tokoh yang amat dikaguminya, atau teologia Thomas Aquinas.
Dalam penelusurannya itu mereka menemukan pelbagai peristiwa haram yang dilakukan oleh para rahib di balik tembok biara. Cerita hubungan seksual sesama jenis dan rasa cemburu antar rahib. Rahib yang lain memasukan perempuan dari kampung sekitar biara untuk melampiaskan syahwat dan menukarnya dengan makanan. Di antara kisah-kisah manusiawi para rahib itu, Eco menguraikan sejarah Abad Tengah Eropa yang kelam oleh perselisihan gereja, politik yang ruwet, filosofi, mitologi, sihir hingga makanan dan tata cara peracikan racun dan obat dengan latar arsitektur zaman Gothik yang eksotik.
Bambang Sugiharto, pengajar filsafat di Universitas Parahiyangan, dalam pengantarnya menulis bahwa novel ini merupakan roman yang kompleks, enigmatik, berlapis-lapis dan menawarkan kemungkinan tafsir terbuka. "Ia bisa dibaca sebagai cerita detektif, cerita sejarah, eksperimentasi teks, parodi petualangan filosofis yang mencari kebenaran, atau apa saja," tulisnya (hal. 15).
Di akhir kisah, William akhirnya mengetahui kematian para rahib itu disebabkan oleh racun yang tersebar di halaman buku dan termakan para rahib yang diterkam rasa ingin tahu saat membolak-balik naskah-naskah kuno itu. Cemburu dan iri hati hanyalah penyebab kecil lain pada tiap kasus kematian. Pelumur racun tak lain adalah Jorge yang tak ingin seorang pun mengetahui kebenaran dalam kitab-kitab yang terhimpun dalam buku Akhir Afrika. Jorge menyimpan kitab itu dalam ruang perpusatakan terra incognita dan siapapun yang menyentuhnya akan mati.
Buku itu sendiri berisi fabel-fabel dalam bahasa Arab yang menjungkirbalikan realitas hingga mengundang gelak tawa. "Misi mereka yang mencintai kemanusiaan adalah untuk membuat manusia tertawa atas kebenaran," kata William pada hari ketujuh saat ia berdebat dengan Jorge tentang makna tawa dan kebenaran. Perdebatan itu kemudian menyulut keributan dan Jorge melemparkan api untuk membakar seluruh naskah itu.
Api merembet dan seluruh harta biara hancur tak bersisa, termasuk Jorge. Maka dengan terbakarnya seluruh kitab di perpustakaan itu, William dan Adso gagal mempertahankan kebenaran yang tersimpan dalam buku dan kebenaran itu hanya menjadi milik mereka berdua. Mereka pulang ke Roma dengan sehimpun kenangan menegangkan di biara itu. Zaman belum berubah, penentang gereja makin bertambah, dan Kaisar Roma telah memilih Paus tandingan: Nicholas V.
Dalam perjalanan kembali itu, William mengatakan bahwa petualangan mereka adalah mencari kebenaran. Dan inilah hakikat dari novel yang mengasyikan ini, meski agak membosankan karena dialog-dialognya yang panjang. Kebenaran bagi William harus terus menerus diragukan, dipertanyakan, untuk mencapai kebenaran yang hakiki. William sendiri tak segan membuang pelbagai hipotesisnya yang tak terbukti dan menajamkan hipotesis lain yang mendekati kebenaran sebagai ramuan kemungkinan penyebab kematian para rahib.
Eco telah dengan tepat memilih cerita detektif untuk mengantarkan pokok-pokok pikirannya. Karena seorang detektif adalah seorang yang mencari. William akan terus menerus bertanya, meramu data, meragukannya, sebelum akhirnya menemukan kebenaran yang diyakininya.
Pernahkan Kristus tertawa? William sendiri menjawab tidak. Tapi ia seorang pembawa pikiran bebas Abad Tengah yang kukuh mempertahankan bahwa humor, satir dan permainan adalah upaya sah hidup manusia. Ia seorang yang yakin manusia perlu untuk ragu pada kebenaran. Dengan terang-terangan ia menyebut Jorge sebagai Sang Iblis. "Iblis adalah arogansi rohani, iman tanpa senyum, kebenaran yang tak pernah dicengkram keraguan," katanya (hal. 631).
Novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Penerjamahnya mengakui butuh nafas panjang untuk menerjemahkan kalimat Eco yang berbelit dan menyimpan tanda yang tak gampang diurai. Agaknya, ia bukan orang Kristen sehingga ada terjemahan yang tak konsisten ketika Injil disebut Bibel, kali lain disebut Al Kitab. Bagaimana pun, buku ini patut disambut karena sebelumnya novel ini sampai ke Indonesia hanya dijumpai sebatas kutipan para esais kendati dalam bahasa aslinya novel ini sudah terbit lebih dari 20 tahun lalu.
Subscribe to:
Comments (Atom)

