: Untuk
Avid yang
risau
Bagi yang khawatir, pernahkah dia mengkhawatirkan kekhawatirannya? Setiap suku lahir, membentuk komunitas, tapi pernahkah mereka, pada mulanya, memproklamirkan kesukuannya. Setiap suku lahir dan nama-nama diberikan kemudian. Kata orang Jawa, kata Sunda berasal dari dua kata: asu dan anda. Dan kita ingat cerita tentang Tumang dalam hikayat Tangkuban Parahu. Setiap anak Sunda pasti tahu cerita yang terkenal ini.
Tumang menjadi tokoh yang tersisih dibanding Dayang Sumbi atau Sang Kuriang. Riwayatnya terhenti ketika Sang Kuriang, anaknya sendiri, membunuhnya saat berburu dan mencongkel hatinya untuk diberikan kepada Dayang Sumbi. Tumang tersisih, bukan karena dia sebagai anjing, tapi karena folklor itu juga, agaknya, tak menginginkan cerita besar yang ingin ditampilkannya mengusung Tumang sebagai salah satu tokohnya. Pengakuan pada Tumang hanya sebatas dia sebagai penyebab Sang Kuriang lahir.
Tumang hadir dalam cerita ini ketika ia mengambilkan "taropong", bambu penggulung benang tenun, milik Dayang Sumbi yang jatuh ke kolong gubuknya yang bertiang tinggi. Dayang Sumbi "terpaksa" menjadikan Tumang sebagai suami karena janji yang telah dibuatnya sendiri: "Bagi laki-laki yang bersedia mengambil kainku akan kujadikan suami, dan bagi perempuan akan kujadikan saudara." Putri raja ini agaknya tak memperhitungkan di hutan yang sunyi akan ada manusia lain yang mendengar janjinya itu. Maka Tumang, anjing jantan itu, datang dan lahirlah Sang Kuriang.
Akibat kebohongan Sang Kuriang yang memberikan hati anjing itu pula, bukan hati kijang, Dayang Sumbi kemudian mengusir anaknya dengan satu tanda ayunan sinduk ke kepala Sang Kuriang. Luka di kepala itu kelak yang membuat Dayang Sumbi tak sangsi, pemuda yang melamarnya tak lain anaknya sendiri. Garis cerita kemudian berkutat antara cinta Sang Kuriang yang ditolak kepada ibunya, pembuatan perahu yang tak rampung, dan seterusnya. Setiap anak Sunda mengira kilat yang mengguntur di langit saat hujan adalah penanda Sang Kuriang hampir berhasil menangkap Dayang Sumbi.
Dalam libretto
Sang Kuriang (1959), Utuy Tatang Sontani meyakini anjing di sana bukan binatang, melainkan manusia tanpa daksa, yang tuli, yang bisu, tapi setia. Manusia golongan rendah yang pasrah, tak bisa mengelak, saat tombak anaknya sendiri menghantam tubuhnya yang ringkih. Hingga kini belum ada yang menganalisis kenapa hikayat itu menciptakan anjing sebagai asal mula sebuah cerita, bukan hewan lain yang lebih terhormat, misalnya. Karena dalam Islam anjing digolongkan ke dalam hewan najis. Juga babi, yang menjadi ibu Dayang Sumbi. Ajip Rosidi dalam
Manusia Sunda (1980) menolak anekdot Jawa yang tak ilmiah itu. Karena hikayat bukan sejarah, katanya. Tapi ia tak membahas lebih detil kenapa anjing yang mempersonfikiasikan Tumang.
Terlepas dari itu, dongeng-dongeng yang hidup di kalangan orang Sunda selalu melukiskan gunung dan sawah, baik sastra klasik, sebelum atau sesudah kemerdakaan, bahkan hingga kini. Dalam sebuah sajaknya, Acep Zamzam Noor menghubungkan seorang petani yang mengayun cangkul, berkutat dengan lumpur di sawah, dalam kesunyian dan kesendirian, dengan gerakan orang yang sedang sembahyang. Dalam
Priangan si Jelita, Ramadhan KH menulis sajak panjang yang mempesona tentang lembah-lembah, sawah, pematang, gunung yang cantik.
Jarang sekali para penayir itu melukiskan Sunda sebagai sebuah metro. Sifat-sifat tokoh dalam sastra Sunda pun tak ada yang keluar dari watak dalam folklor yang dimiliki Si Kabayan, Mundinglaya di Kusumah, Purbasari Ayu Wangi, atau Sang Kuriang yang teguh pendirian. Sosok Kabayan muncul dalam Cepot yang doyan banyol dalam wayang golek atau Karnadi dalam cerita
Rusiah Nu Goreng Patut (1927) karangan Joehana. Sifat Mundinglaya sebagai ksatria muncul dalam diri Raden Yogaswara sebagai
Mantri Jero karya R Memed Sastrahadiprawira. Atau sifat kedewian Purbasari muncul dalam Dewi Pramanik dalam
wawacan Purnama Alam karya R Suriadiredja. Agaknya folklor di manapun, selalu muncul seiring dengan keinginan komunitas itu untuk menampilkan identitasnya dalam bentuk sastra lisan. Kota, agaknya, dianggap tak membumi.
Orang Sunda juga tak pernah ekslusif. Setiap cerita dalam sastra atau folklor selalu menampilkan tokoh utama yang keluar dari tanah kelahiran--meski agak mengherankan kenapa orang Sunda tak terkenal sebagai bangsa perantau. Padahal, dalam satu cerita tertua yang mengisahkan penemuan agama Islam mula-mula di Cirebon, tokoh utama sejarah itu melanglang hingga ke Jawa. Islam kemudian memang agama yang paling diterima oleh orang Sunda yang masih menganut Hindu atau Wiwitan. Barangkali, karena orang Sunda--juga seperti orang Jawa--menganut falsafah "mangan ora mangan asal kumpul".
Sejarah Sunda juga mengisahkan keterbukaan menerima budaya dari bukan Sunda. Ketika pasukan Mataram mendarat di pesisir Banten, misalnya, kemudian melahirkan barter barang antara tentara Mataram dengan orang Kanekes di sana. Mataram yang pesisir menukarkan ikan dan hasil laut lainnya dengan kebutuhan dari hasil pertanian. Orang Sunda, mula-mula, hidup di gunung-gunung. Mereka terdesak oleh budaya Utara yang lebih radikal. Mereka selalu menghargai tamu--bahkan menghormatinya sebagai pembawa budaya yang lebih maju (paling tidak tamu adalah orang yang berpesiar)--sesuai dengan falsafah "datang katempo tarang, indit katempo birit". Tamu yang menghormati sopan santun akan lebih dihormati lagi, bahkan secara tak sadar, jika ia menyebarkan misi budayanya. Para penulis sastra kuno di Sunda pun, begitu catatan Ajip, bukan lahir dari orang Sunda murni. Mereka datang ke Sunda karena salah satu orang tuanya kawin dengan orang Sunda lalu menentap di sana. Mien Resmana yang
carita-carita pondok-nya selalu menarik punya Bapak orang Bugis.
Karena itu Avid, menampilkan Sunda dengan lebih terhormat, menurut saya, bukan dengan memunculkan ekslusifitas, gaya, dan bungkusnya. Budaya Sunda, sejak lahir, sudah mendekam dan muncul dalam komunitas Sunda sendiri. Sebab itu juga, menurut saya, kesundaan juga tak akan punah. Jika sekarang Bandung, sebagai pusat Sunda (benarkah penyebutan ini?) sudah didominasi oleh sifat-sifat metro, itu hanya karena ke Bandung telah menyerap apa yang disebut lanskap kota. Kota, kata Raymond Williams, (adalah lanskap besar yang) selalu menampilkan kesunyian dan keterpencilan dari identitas asalnya. Cobalah kita tengok ke selain Bandung, apa yang disebut Kesundaan di sana masih muncul. Dulu, di depan Balai Kota Bogor setiap malam minggu selalu ditampilkan wayang golek atau calung. Orang Bogor berduyun menonton pentas itu.
Saya khawatir Kesundaan yang dibungkus dengan ekslusifitas, yang mentereng, hanya akan memberhentikan Kesundaan sebatas panggung--lengkap dengan birokratisasi segala. Maka biarkanlah Kesundaan itu muncul dan merembes di setiap jiwa orang-orang Sunda baik yang di komunitas yang getol, mapun di luarnya. Saya kira,
Mangle yang berkertas
Cosmopolitan itu agak aneh juga jika cerita pendek di sana menceritakan bagaimana orang seperti Karnadi
ngadu untung ka kota. Lakon
Perjuangan Suku Naga WS Rendra agaknya pas melukiskan itu. Di sana apa yang "kota" pada akhirnya memenangkan pergulatan. Tapi ini zaman ketika kapitalisme sudah diamini banyak orang baik sadar atau tak sadar, dan gaungnya sampai ke pelosok dibawa oleh "Karnadi-Karnadi" yang pulang kampung. Jika anak-anak Sunda sekarang jarang berbahasa Sunda, itu karena sedikitnya orang Sunda yang mau menulis dengan getol dan melahirkan tulisan-tulisan yang punya ruh Sunda yang kuat. Sebagai "pemerhati" tentu saja dikau harus tertantang.
Ada banyak hal yang belum terungkap dalam sejarah Sunda yang panjang. Ada bahan perdebatan menarik, sebenarnya, ketika Ayatrohaedi meragukan nenek moyang orang Sunda. Menurut tulisannya di
Pikiran Rakyat, nenek moyang orang Sunda bukan Ciung Wanara. Seharusnya ini didebatkan, karena dalam pantun lisan, kita tahu, Ciung Wanara adalah orang yang diklaim nenek moyang orang Sunda, yang bertempur melawan Hariang Banga di tepi sungai Cipamali. Menurut Ayat, pengakuan itu barangkali dipicu oleh asal turunan. Ciung Wanara adalah anak dari istri yang sah Ranghyang Sanjaya, bukan anak selir seperti Banga. Ini baru praduga yang seharusnya ditelusuri untuk menemukan mana yang benar. Juga sejarah Ciung Wanara sendiri yang namanya tenar hingga ke Bali--di sana I Gusti Ngurah Rai memimpin laskar yang diberi nama Ciung Wanara. Ini dunia yang tak habis-habis untuk diteliti dan diperbincangkan. Karena itu, Vid, pernahkah khawatir dengan kekhawatiranmu?
UPDATE:
Avid menuliskan tanggapannya di
sini
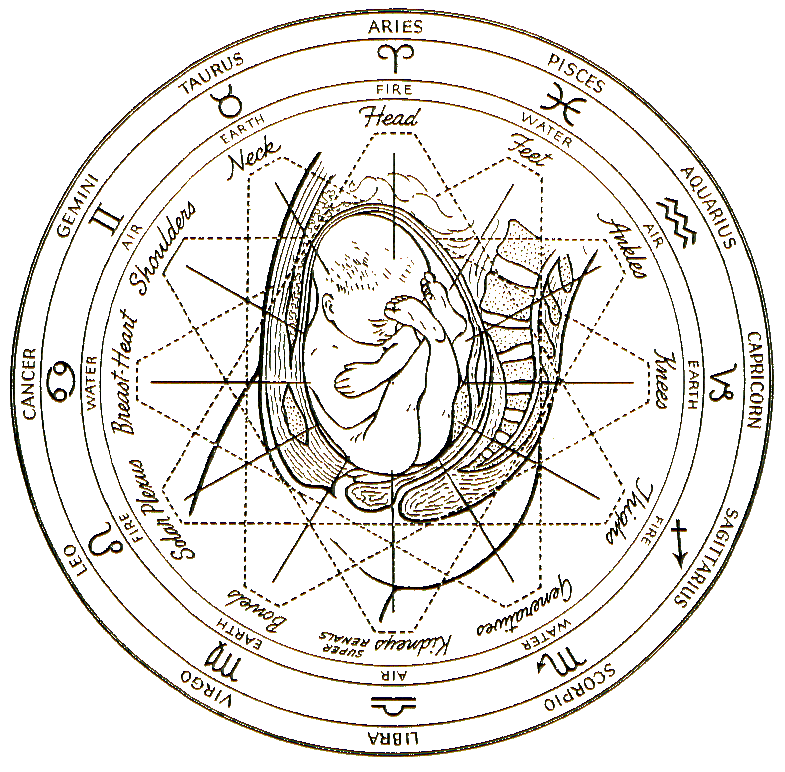 Aku menunggumu, Bayi, datang pada pelukan pada setiap sore yang anggun. Aku menunggumu, dengan debar yang tak bisa dirumuskan. Aku menunggumu, bukan karena aku telah meniupkan rabu di rahim ibumu. Aku menunggumu, karena aku mencemaskan sebuah petang yang tak tentram ketika ibumu berhenti menyulam.
Aku menunggumu, Bayi, datang pada pelukan pada setiap sore yang anggun. Aku menunggumu, dengan debar yang tak bisa dirumuskan. Aku menunggumu, bukan karena aku telah meniupkan rabu di rahim ibumu. Aku menunggumu, karena aku mencemaskan sebuah petang yang tak tentram ketika ibumu berhenti menyulam.